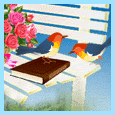AKU DAN SASTRA
Thursday, March 20, 2008,11:14 PM
 HASAN ASPAHANI
HASAN ASPAHANI
“…..saya ingin jadi orang lain”
“Saya mulai menulis puisi kelas 2 SMP,” ujar Hasan Aspahani memulai percakapan malam itu (19/3) di sebuah café di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Ia tampak sedikit letih karena seharian sibuk mengikuti acara diskusi dengan seorang menteri. Tidak banyak yang berubah dari pria kelahiran 9 Maret 1971 ini sejak terakhir kali saya bertemu dengannya akhir tahun silam. Masih gempal dan brewokan.
Hasan lahir di kota kecil Samboja, 80 km dari Balikpapan, Kalimantan Timur dari pasangan ayah asli Banjarmasin dan ibu keturunan Jawa. Anak kedua dari empat bersaudara ini menghabiskan masa remajanya di kota kecil itu sebelum kemudian merantau ke Balikpapan untuk melanjutkan studinya di SMA.
Perkenalan pertamanya dengan puisi terjadi saat ia masih duduk di bangku madrasah tsanawiyah (setingkat SMP). Karya-karya Rendra dan Chairil Anwar mengantarkannya memasuki dunia sastra, khususnya puisi. Ia sangat terkesan dengan sajak “Terbunuhnya Atmo Karpo” (W.S. Rendra). Waktu itu ia sangat kepingin bisa bikin sajak seperti itu.
Namun, tatkala SMA selera bersajaknya berubah drastis setelah “bertemu” dengan Sapardi Djoko Damono lewat buku DukaMu Abadi. Dalam buku kumpulan puisi ini Hasan menemukan “keajaiban” melalui rangkaian kata-kata sehari-hari yang bersahaja. “Sapardi membuat saya ‘gila’,” kenangnya dengan nada suara penuh kekaguman terhadap penyair gaek tersebut. Ia tinggalkan Rendra untuk kemudian “memuja dewa” barunya : Sapardi. Tak heran jika dalam karya-karya awal Hasan terasa sekali pengaruh Sapardi yang sangat kuat. Tapi, siapa sih yang tidak terkena “sihir” Penyair Hujan itu?
Tentang kepenyairan Hasan itu sudah banyak yang mafhum. Tetapi siapa sangka ternyata ayah dua anak ini juga pandai membuat kartun. Ia bahkan sempat mengisi secara rutin rubrik kartun (komik strip) di surat kabar daerah Manuntung di Balikpapan selama 3 tahun. Nama kartunnya adalah Ketupat, singkatan dari Kelas Satu Empat, kelas Hasan di SMA saat ia mulai membuat kartun tersebut. Honor yang didapatnya dibelikan buku-buku. Salah satu buku favoritnya adalah Mengarang Itu Gampang karya Arswendo Atmowiloto. “Saya selalu merekomendasikan buku tersebut kepada mereka yang hendak menjadi penulis,” jelas Hasan sambil memainkan telepon selulernya.
Pada 1990 ia diterima di IPB (Institut Pertanian Bogor) melalui jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan). Pada tahun kedua ia mengambil jurusan Ilmu Tanah. Sungguh jauh memang dari pekerjaan yang ditekuninya kini selaku pemimpin redaksi di sebuah koran di Batam. “Saya memang bercita-cita jadi wartawan, bukan penyair,” kata ayah dari Shiela Mutianda (9) dan Ikra Bhaktiananda (4).
Di kampus IPB ini Hasan berjumpa dengan Dhiana, gadis teman sekelas yang sejak sembilan tahun lalu resmi menjadi istrinya. Sementara itu “perkawinannya” dengan puisi terus berlanjut mencari bentuk. Pada awal tahun 2000 ia menemukan Celana Joko Pinurbo. Seperti saat pertama “mengenal” Sapardi, kali ini pun Hasan dibuat “gila” sekaligus cemburu pada sajak-sajak Jokpin. Ia pun lantas menjalin “perselingkuhan” dengan Jokpin tanpa benar-benar meninggalkan Sapardi. Ia mengakui, bahwa kedua penyair tersebut sangat berpengaruh pada karya-karyanya. “Mereka idola saya selain Neruda”.
Oh ya, belakangan Hasan jatuh cinta sangat kepada sajak-sajak penyair Cile itu. Ia tidak tahan untuk tidak menerjemahkan soneta dan puisi-puisi cinta Si Pablo. “Fiiuuuh…..sajak cinta Neruda itu dahsyat!” (Ia lalu melafalkan dengan fasihnya sebait soneta cinta Neruda).
Rasanya semua keinginan masa kecil telah diraihnya. Sekarang yang paling diinginkannya adalah tinggal di sebuah kota kecil di Eropa, di mana tidak ada orang-orang yang mengenalnya. “Kalau saya dilahirkan kembali, saya ingin jadi orang lain. Bosan jadi Hasan Aspahani. Ha..ha..ha..,” tawanya pecah, mengakhiri percakapan kami.***ENDAH SULWESI
Hasan lahir di kota kecil Samboja, 80 km dari Balikpapan, Kalimantan Timur dari pasangan ayah asli Banjarmasin dan ibu keturunan Jawa. Anak kedua dari empat bersaudara ini menghabiskan masa remajanya di kota kecil itu sebelum kemudian merantau ke Balikpapan untuk melanjutkan studinya di SMA.
Perkenalan pertamanya dengan puisi terjadi saat ia masih duduk di bangku madrasah tsanawiyah (setingkat SMP). Karya-karya Rendra dan Chairil Anwar mengantarkannya memasuki dunia sastra, khususnya puisi. Ia sangat terkesan dengan sajak “Terbunuhnya Atmo Karpo” (W.S. Rendra). Waktu itu ia sangat kepingin bisa bikin sajak seperti itu.
Namun, tatkala SMA selera bersajaknya berubah drastis setelah “bertemu” dengan Sapardi Djoko Damono lewat buku DukaMu Abadi. Dalam buku kumpulan puisi ini Hasan menemukan “keajaiban” melalui rangkaian kata-kata sehari-hari yang bersahaja. “Sapardi membuat saya ‘gila’,” kenangnya dengan nada suara penuh kekaguman terhadap penyair gaek tersebut. Ia tinggalkan Rendra untuk kemudian “memuja dewa” barunya : Sapardi. Tak heran jika dalam karya-karya awal Hasan terasa sekali pengaruh Sapardi yang sangat kuat. Tapi, siapa sih yang tidak terkena “sihir” Penyair Hujan itu?
Tentang kepenyairan Hasan itu sudah banyak yang mafhum. Tetapi siapa sangka ternyata ayah dua anak ini juga pandai membuat kartun. Ia bahkan sempat mengisi secara rutin rubrik kartun (komik strip) di surat kabar daerah Manuntung di Balikpapan selama 3 tahun. Nama kartunnya adalah Ketupat, singkatan dari Kelas Satu Empat, kelas Hasan di SMA saat ia mulai membuat kartun tersebut. Honor yang didapatnya dibelikan buku-buku. Salah satu buku favoritnya adalah Mengarang Itu Gampang karya Arswendo Atmowiloto. “Saya selalu merekomendasikan buku tersebut kepada mereka yang hendak menjadi penulis,” jelas Hasan sambil memainkan telepon selulernya.
Pada 1990 ia diterima di IPB (Institut Pertanian Bogor) melalui jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan). Pada tahun kedua ia mengambil jurusan Ilmu Tanah. Sungguh jauh memang dari pekerjaan yang ditekuninya kini selaku pemimpin redaksi di sebuah koran di Batam. “Saya memang bercita-cita jadi wartawan, bukan penyair,” kata ayah dari Shiela Mutianda (9) dan Ikra Bhaktiananda (4).
Di kampus IPB ini Hasan berjumpa dengan Dhiana, gadis teman sekelas yang sejak sembilan tahun lalu resmi menjadi istrinya. Sementara itu “perkawinannya” dengan puisi terus berlanjut mencari bentuk. Pada awal tahun 2000 ia menemukan Celana Joko Pinurbo. Seperti saat pertama “mengenal” Sapardi, kali ini pun Hasan dibuat “gila” sekaligus cemburu pada sajak-sajak Jokpin. Ia pun lantas menjalin “perselingkuhan” dengan Jokpin tanpa benar-benar meninggalkan Sapardi. Ia mengakui, bahwa kedua penyair tersebut sangat berpengaruh pada karya-karyanya. “Mereka idola saya selain Neruda”.
Oh ya, belakangan Hasan jatuh cinta sangat kepada sajak-sajak penyair Cile itu. Ia tidak tahan untuk tidak menerjemahkan soneta dan puisi-puisi cinta Si Pablo. “Fiiuuuh…..sajak cinta Neruda itu dahsyat!” (Ia lalu melafalkan dengan fasihnya sebait soneta cinta Neruda).
Rasanya semua keinginan masa kecil telah diraihnya. Sekarang yang paling diinginkannya adalah tinggal di sebuah kota kecil di Eropa, di mana tidak ada orang-orang yang mengenalnya. “Kalau saya dilahirkan kembali, saya ingin jadi orang lain. Bosan jadi Hasan Aspahani. Ha..ha..ha..,” tawanya pecah, mengakhiri percakapan kami.***ENDAH SULWESI
posted by biru
Permalink ¤
Permalink ¤