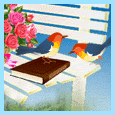AKU DAN SASTRA
Thursday, March 20, 2008,11:14 PM
 HASAN ASPAHANI
HASAN ASPAHANI“…..saya ingin jadi orang lain”
“Saya mulai menulis puisi kelas 2 SMP,” ujar Hasan Aspahani memulai percakapan malam itu (19/3) di sebuah café di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Ia tampak sedikit letih karena seharian sibuk mengikuti acara diskusi dengan seorang menteri. Tidak banyak yang berubah dari pria kelahiran 9 Maret 1971 ini sejak terakhir kali saya bertemu dengannya akhir tahun silam. Masih gempal dan brewokan.
Hasan lahir di kota kecil Samboja, 80 km dari Balikpapan, Kalimantan Timur dari pasangan ayah asli Banjarmasin dan ibu keturunan Jawa. Anak kedua dari empat bersaudara ini menghabiskan masa remajanya di kota kecil itu sebelum kemudian merantau ke Balikpapan untuk melanjutkan studinya di SMA.
Perkenalan pertamanya dengan puisi terjadi saat ia masih duduk di bangku madrasah tsanawiyah (setingkat SMP). Karya-karya Rendra dan Chairil Anwar mengantarkannya memasuki dunia sastra, khususnya puisi. Ia sangat terkesan dengan sajak “Terbunuhnya Atmo Karpo” (W.S. Rendra). Waktu itu ia sangat kepingin bisa bikin sajak seperti itu.
Namun, tatkala SMA selera bersajaknya berubah drastis setelah “bertemu” dengan Sapardi Djoko Damono lewat buku DukaMu Abadi. Dalam buku kumpulan puisi ini Hasan menemukan “keajaiban” melalui rangkaian kata-kata sehari-hari yang bersahaja. “Sapardi membuat saya ‘gila’,” kenangnya dengan nada suara penuh kekaguman terhadap penyair gaek tersebut. Ia tinggalkan Rendra untuk kemudian “memuja dewa” barunya : Sapardi. Tak heran jika dalam karya-karya awal Hasan terasa sekali pengaruh Sapardi yang sangat kuat. Tapi, siapa sih yang tidak terkena “sihir” Penyair Hujan itu?
Tentang kepenyairan Hasan itu sudah banyak yang mafhum. Tetapi siapa sangka ternyata ayah dua anak ini juga pandai membuat kartun. Ia bahkan sempat mengisi secara rutin rubrik kartun (komik strip) di surat kabar daerah Manuntung di Balikpapan selama 3 tahun. Nama kartunnya adalah Ketupat, singkatan dari Kelas Satu Empat, kelas Hasan di SMA saat ia mulai membuat kartun tersebut. Honor yang didapatnya dibelikan buku-buku. Salah satu buku favoritnya adalah Mengarang Itu Gampang karya Arswendo Atmowiloto. “Saya selalu merekomendasikan buku tersebut kepada mereka yang hendak menjadi penulis,” jelas Hasan sambil memainkan telepon selulernya.
Pada 1990 ia diterima di IPB (Institut Pertanian Bogor) melalui jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan). Pada tahun kedua ia mengambil jurusan Ilmu Tanah. Sungguh jauh memang dari pekerjaan yang ditekuninya kini selaku pemimpin redaksi di sebuah koran di Batam. “Saya memang bercita-cita jadi wartawan, bukan penyair,” kata ayah dari Shiela Mutianda (9) dan Ikra Bhaktiananda (4).
Di kampus IPB ini Hasan berjumpa dengan Dhiana, gadis teman sekelas yang sejak sembilan tahun lalu resmi menjadi istrinya. Sementara itu “perkawinannya” dengan puisi terus berlanjut mencari bentuk. Pada awal tahun 2000 ia menemukan Celana Joko Pinurbo. Seperti saat pertama “mengenal” Sapardi, kali ini pun Hasan dibuat “gila” sekaligus cemburu pada sajak-sajak Jokpin. Ia pun lantas menjalin “perselingkuhan” dengan Jokpin tanpa benar-benar meninggalkan Sapardi. Ia mengakui, bahwa kedua penyair tersebut sangat berpengaruh pada karya-karyanya. “Mereka idola saya selain Neruda”.
Oh ya, belakangan Hasan jatuh cinta sangat kepada sajak-sajak penyair Cile itu. Ia tidak tahan untuk tidak menerjemahkan soneta dan puisi-puisi cinta Si Pablo. “Fiiuuuh…..sajak cinta Neruda itu dahsyat!” (Ia lalu melafalkan dengan fasihnya sebait soneta cinta Neruda).
Rasanya semua keinginan masa kecil telah diraihnya. Sekarang yang paling diinginkannya adalah tinggal di sebuah kota kecil di Eropa, di mana tidak ada orang-orang yang mengenalnya. “Kalau saya dilahirkan kembali, saya ingin jadi orang lain. Bosan jadi Hasan Aspahani. Ha..ha..ha..,” tawanya pecah, mengakhiri percakapan kami.***ENDAH SULWESI
Hasan lahir di kota kecil Samboja, 80 km dari Balikpapan, Kalimantan Timur dari pasangan ayah asli Banjarmasin dan ibu keturunan Jawa. Anak kedua dari empat bersaudara ini menghabiskan masa remajanya di kota kecil itu sebelum kemudian merantau ke Balikpapan untuk melanjutkan studinya di SMA.
Perkenalan pertamanya dengan puisi terjadi saat ia masih duduk di bangku madrasah tsanawiyah (setingkat SMP). Karya-karya Rendra dan Chairil Anwar mengantarkannya memasuki dunia sastra, khususnya puisi. Ia sangat terkesan dengan sajak “Terbunuhnya Atmo Karpo” (W.S. Rendra). Waktu itu ia sangat kepingin bisa bikin sajak seperti itu.
Namun, tatkala SMA selera bersajaknya berubah drastis setelah “bertemu” dengan Sapardi Djoko Damono lewat buku DukaMu Abadi. Dalam buku kumpulan puisi ini Hasan menemukan “keajaiban” melalui rangkaian kata-kata sehari-hari yang bersahaja. “Sapardi membuat saya ‘gila’,” kenangnya dengan nada suara penuh kekaguman terhadap penyair gaek tersebut. Ia tinggalkan Rendra untuk kemudian “memuja dewa” barunya : Sapardi. Tak heran jika dalam karya-karya awal Hasan terasa sekali pengaruh Sapardi yang sangat kuat. Tapi, siapa sih yang tidak terkena “sihir” Penyair Hujan itu?
Tentang kepenyairan Hasan itu sudah banyak yang mafhum. Tetapi siapa sangka ternyata ayah dua anak ini juga pandai membuat kartun. Ia bahkan sempat mengisi secara rutin rubrik kartun (komik strip) di surat kabar daerah Manuntung di Balikpapan selama 3 tahun. Nama kartunnya adalah Ketupat, singkatan dari Kelas Satu Empat, kelas Hasan di SMA saat ia mulai membuat kartun tersebut. Honor yang didapatnya dibelikan buku-buku. Salah satu buku favoritnya adalah Mengarang Itu Gampang karya Arswendo Atmowiloto. “Saya selalu merekomendasikan buku tersebut kepada mereka yang hendak menjadi penulis,” jelas Hasan sambil memainkan telepon selulernya.
Pada 1990 ia diterima di IPB (Institut Pertanian Bogor) melalui jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan). Pada tahun kedua ia mengambil jurusan Ilmu Tanah. Sungguh jauh memang dari pekerjaan yang ditekuninya kini selaku pemimpin redaksi di sebuah koran di Batam. “Saya memang bercita-cita jadi wartawan, bukan penyair,” kata ayah dari Shiela Mutianda (9) dan Ikra Bhaktiananda (4).
Di kampus IPB ini Hasan berjumpa dengan Dhiana, gadis teman sekelas yang sejak sembilan tahun lalu resmi menjadi istrinya. Sementara itu “perkawinannya” dengan puisi terus berlanjut mencari bentuk. Pada awal tahun 2000 ia menemukan Celana Joko Pinurbo. Seperti saat pertama “mengenal” Sapardi, kali ini pun Hasan dibuat “gila” sekaligus cemburu pada sajak-sajak Jokpin. Ia pun lantas menjalin “perselingkuhan” dengan Jokpin tanpa benar-benar meninggalkan Sapardi. Ia mengakui, bahwa kedua penyair tersebut sangat berpengaruh pada karya-karyanya. “Mereka idola saya selain Neruda”.
Oh ya, belakangan Hasan jatuh cinta sangat kepada sajak-sajak penyair Cile itu. Ia tidak tahan untuk tidak menerjemahkan soneta dan puisi-puisi cinta Si Pablo. “Fiiuuuh…..sajak cinta Neruda itu dahsyat!” (Ia lalu melafalkan dengan fasihnya sebait soneta cinta Neruda).
Rasanya semua keinginan masa kecil telah diraihnya. Sekarang yang paling diinginkannya adalah tinggal di sebuah kota kecil di Eropa, di mana tidak ada orang-orang yang mengenalnya. “Kalau saya dilahirkan kembali, saya ingin jadi orang lain. Bosan jadi Hasan Aspahani. Ha..ha..ha..,” tawanya pecah, mengakhiri percakapan kami.***ENDAH SULWESI
Wednesday, March 12, 2008,12:31 PM
 TIGA PEREMPUAN MENUNTUT MALAM
TIGA PEREMPUAN MENUNTUT MALAMDalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, Institut Ungu dan Yayasan Pitaloka menggelar pentas teater monolog bertajuk Perempuan Menuntut Malam. Institut Ungu adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergiat mengampanyekan isu-isu perempuan melalui seni budaya. Organisasi ini berdiri pada 18 Juli 2002 di Jakarta berkat gagasan Yeni Rosa Damayanti, Faiza Mardzoeki, Irina Dayasih, dan Nur Rachmi. Sejak terbentuknya, Institut Ungu telah beberapa kali mengadakan rangkaian kegiatan seni budaya yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berekspresi sekaligus menyampaikan perspektif seluas-luasnya kepada masyarakat.
Adapun Yayasan Pitaloka, dibentuk oleh Rieke Diah Pitaloka dua tahun lalu, adalah organisasi yang didedikasikan secara khusus kepada “Demokrasi dan Kemanusiaan”, terutama bagi anak-anak dan perempuan.
Tahun ini, kedua organisasi tersebut berkolaborasi menyelenggarakan pertunjukan teater monolog Perempuan Menuntut Malam yang akan tampil di tiga kota : Jakarta (8-9 Maret), Banda Aceh (24/3), dan Bandung (28-29 Maret).
Pada pertunjukan di Jakarta dua pekan silam ketiga aktris yang tampil, Niniek L.karim, Rieke Diah Pitaloka, dan Ria Irawan, cukup berhasil membawakan masing-masing peran mereka.
Niniek L. Karim kebagian tampil pertama, memerankan tokoh Ranti, seorang ibu rumah tangga yang memutuskan bercerai karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari sang suami. Bertahun-tahun kemudian Ranti tenryata harus berhadapan kembali dengan masalah yang sama. Hanya saja kali ini yang mengalami adalah putrinya. Niniek sukses membawakan perannya dengan kualitas akting yang tak perlu dipertanyakan lagi. Aktris yang mengasah bakat aktingnya di Teater Populer ini tampak tak mengalami kesulitan dengan perannya sebagai Ranti.
Berikutnya adalah Rieke Diah Pitaloka yang mewujud dalam karakter Ani, perempuan dengan peran ganda sebagai istri, ibu, sekaligus politisi. Ia kerap kali mendapat perlakuan bias gender dari media dan masyarakat. Misalnya saja, dalam wawancara ia lebih sering mendapat pertanyaan seputar rumah tangganya ketimbang pertanyaan-pertanyaan ikhwal dunia politik yang menjadi keahliannya. Dengan gayanya yang kocak menyindir, aktris sinetron yang juga aktivis ini mampu menghidupkan peran tersebut. Siasat penggunaan layar dan siluet (seperti dalam pertunjukan wayang) untuk adegan di kamar mandi cukup menarik, meskipun bukan sesuatu yang baru. Sayangnya, naskah yang sebenarnya sudah cukup cerdas, tidak sanggup menahan godaan untuk “berpidato” di bagian akhir.
Penampil ketiga adalah Ria Irawan. Aktris film senior yang memiliki nama lengkap Chandra Ariati Dewi ini mendapat bagian memerankan tokoh Khadijah, seorang pekerja seks komersial (PSK) “indie” (tidak punya germo) yang mangkal di bawah lampu jalanan Sebagai Khadijah, Ria kembali membuktikan kehandalan aktingnya di panggung teater. Karakter Khadijah yang kenes, genit, liar, dan nyeleneh begitu hidup dimainkannya.
Naskah yang ditulis oleh Faiza Mardzoeki dan Rieke Diah Pitaloka ini pada pokoknya ingin mengetengahkan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan sehari-hari dalam lingkup rumah, seks, politik, dan kekuasaan. Sampai hari ini masih banyak perempuan yang mengalami penindasan, kekerasan, dan diskriminasi dalam banyak hal. Melalui pementasan ini diharapkan bisa membuka wawasan dan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, untuk bersama-sama menentang segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut. Untuk lebih mendukung upaya penyadaran tersebut, selama pementasan berlangsung dipamerkan pula sejumlah foto dan poster di lobby Graha Bakti Budaya, TIM, Jakarta.
Secara keseluruhan, pentas yang digarap oleh sutradara Zuki a.k.a. Kill The DJ ini, cukup memikat. Suasana realis cukup terwakilkan oleh tata panggung minimalis dan penggunaan videografi. Pertunjukan selanjutnya di Banda Aceh akan menggandeng Komunitas Tikar Pandan dan di Bandung dengan Main Teater. ***
Adapun Yayasan Pitaloka, dibentuk oleh Rieke Diah Pitaloka dua tahun lalu, adalah organisasi yang didedikasikan secara khusus kepada “Demokrasi dan Kemanusiaan”, terutama bagi anak-anak dan perempuan.
Tahun ini, kedua organisasi tersebut berkolaborasi menyelenggarakan pertunjukan teater monolog Perempuan Menuntut Malam yang akan tampil di tiga kota : Jakarta (8-9 Maret), Banda Aceh (24/3), dan Bandung (28-29 Maret).
Pada pertunjukan di Jakarta dua pekan silam ketiga aktris yang tampil, Niniek L.karim, Rieke Diah Pitaloka, dan Ria Irawan, cukup berhasil membawakan masing-masing peran mereka.
Niniek L. Karim kebagian tampil pertama, memerankan tokoh Ranti, seorang ibu rumah tangga yang memutuskan bercerai karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari sang suami. Bertahun-tahun kemudian Ranti tenryata harus berhadapan kembali dengan masalah yang sama. Hanya saja kali ini yang mengalami adalah putrinya. Niniek sukses membawakan perannya dengan kualitas akting yang tak perlu dipertanyakan lagi. Aktris yang mengasah bakat aktingnya di Teater Populer ini tampak tak mengalami kesulitan dengan perannya sebagai Ranti.
Berikutnya adalah Rieke Diah Pitaloka yang mewujud dalam karakter Ani, perempuan dengan peran ganda sebagai istri, ibu, sekaligus politisi. Ia kerap kali mendapat perlakuan bias gender dari media dan masyarakat. Misalnya saja, dalam wawancara ia lebih sering mendapat pertanyaan seputar rumah tangganya ketimbang pertanyaan-pertanyaan ikhwal dunia politik yang menjadi keahliannya. Dengan gayanya yang kocak menyindir, aktris sinetron yang juga aktivis ini mampu menghidupkan peran tersebut. Siasat penggunaan layar dan siluet (seperti dalam pertunjukan wayang) untuk adegan di kamar mandi cukup menarik, meskipun bukan sesuatu yang baru. Sayangnya, naskah yang sebenarnya sudah cukup cerdas, tidak sanggup menahan godaan untuk “berpidato” di bagian akhir.
Penampil ketiga adalah Ria Irawan. Aktris film senior yang memiliki nama lengkap Chandra Ariati Dewi ini mendapat bagian memerankan tokoh Khadijah, seorang pekerja seks komersial (PSK) “indie” (tidak punya germo) yang mangkal di bawah lampu jalanan Sebagai Khadijah, Ria kembali membuktikan kehandalan aktingnya di panggung teater. Karakter Khadijah yang kenes, genit, liar, dan nyeleneh begitu hidup dimainkannya.
Naskah yang ditulis oleh Faiza Mardzoeki dan Rieke Diah Pitaloka ini pada pokoknya ingin mengetengahkan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan sehari-hari dalam lingkup rumah, seks, politik, dan kekuasaan. Sampai hari ini masih banyak perempuan yang mengalami penindasan, kekerasan, dan diskriminasi dalam banyak hal. Melalui pementasan ini diharapkan bisa membuka wawasan dan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, untuk bersama-sama menentang segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut. Untuk lebih mendukung upaya penyadaran tersebut, selama pementasan berlangsung dipamerkan pula sejumlah foto dan poster di lobby Graha Bakti Budaya, TIM, Jakarta.
Secara keseluruhan, pentas yang digarap oleh sutradara Zuki a.k.a. Kill The DJ ini, cukup memikat. Suasana realis cukup terwakilkan oleh tata panggung minimalis dan penggunaan videografi. Pertunjukan selanjutnya di Banda Aceh akan menggandeng Komunitas Tikar Pandan dan di Bandung dengan Main Teater. ***
Monday, March 03, 2008,2:49 PM
 DINO F.UMAHUK DAN METAFORA BIRAHI LAUT
DINO F.UMAHUK DAN METAFORA BIRAHI LAUTRabu malam pekan silam (27/2), Warung Apresiasi (Wapres) Bulungan tampak ramai. Orang-orang muda satu per satu tampak bermunculan di sana. Lelaki dan perempuan. Mereka datang untuk menghadiri acara peluncuran buku kumpulan puisi Dino F.Umahuk yang diberi judul Metafora Birahi Laut.
Perhelatan yang berlangsung dari pukul 20.00 sampai menjelang pukul 22.00 itu dimeriahkan oleh berbagai acara. Ada diskusi buku dengan menampilkan cerpenis Kurnia Effendi sebagai pembicara, pembacaan puisi di antaranya oleh Yonathan Rahardjo dan Budi Setyawan, serta pementasan mini drama oleh kelompok Teater Pintu STBA LIA, Jakarta.
Buku perdananya ini memuat 127 buah puisi yang dibuat sepanjang tahun 2000 hingga 2007. “Ini adalah buah perjalanan dari lika-liku dan luka hidup saya,” ungkap Dino mengenai riwayat bukunya. Sejatinya, lelaki berdarah Ambon ini telah menulis puisi jauh sebelum tahun 2000. Tetapi kerusuhan Ambon pada 1999 telah membakar habis arsip-arsip yang berisi sajak miliknya. Tanpa sisa.
Dino yang lahir pada 1 Oktober 1974 ini menghabiskan masa remajanya di Ambon. Selain menekuni puisi, pria berkulit gelap ini sehari-harinya aktif sebagai Program Peace Building di Bappenas untuk reintegrasi dan perdamaian Aceh. Tak heran jika ia sering bolak-balik Jakarta-Banda Aceh.
Dalam makalahnya, Kurnia Effendi menulis, bahwa pembicaraan tentang laut (dalam hal metafora, sebagai latar tempat, personifikasi, maupun esensi) sangat karib dalam puisi Dino. Boleh jadi ini menunjukkan kedekatan penyairnya dengan laut sebagai lingkungan yang membesarkan dan atau menjadi obsesinya. Sebagai orang Indonesia bagian Timur, tepatnya Ambon, sekaligus sebagai cucu dari moyang Nusantara yang konon para pelaut, sudah seharusnya manusia Indonesia memiliki “darah” kelautan.
Sementara Ikranegara, budayawan yang kini mukim di Amerika Serikat, dalam kata pengantar di buku tersebut mengatakan, bahwa puisi-puisi Dino lahir karena adanya kegalauan yang sangat manusiawi dalam menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dia alami sendiri; baik itu kejadian sosial politik, maupun yang terjadi atas diri pribadi.
Terlepas dari penilaian keduanya, kita berharap agar buku ini tidak lalu sekadar menjadi penanda kepenyairan seorang Dino Flores Umahuk, tetapi juga bisa ikut memberi kontribusi yang berarti bagi kekayaan ranah sastra Indonesia.***
Perhelatan yang berlangsung dari pukul 20.00 sampai menjelang pukul 22.00 itu dimeriahkan oleh berbagai acara. Ada diskusi buku dengan menampilkan cerpenis Kurnia Effendi sebagai pembicara, pembacaan puisi di antaranya oleh Yonathan Rahardjo dan Budi Setyawan, serta pementasan mini drama oleh kelompok Teater Pintu STBA LIA, Jakarta.
Buku perdananya ini memuat 127 buah puisi yang dibuat sepanjang tahun 2000 hingga 2007. “Ini adalah buah perjalanan dari lika-liku dan luka hidup saya,” ungkap Dino mengenai riwayat bukunya. Sejatinya, lelaki berdarah Ambon ini telah menulis puisi jauh sebelum tahun 2000. Tetapi kerusuhan Ambon pada 1999 telah membakar habis arsip-arsip yang berisi sajak miliknya. Tanpa sisa.
Dino yang lahir pada 1 Oktober 1974 ini menghabiskan masa remajanya di Ambon. Selain menekuni puisi, pria berkulit gelap ini sehari-harinya aktif sebagai Program Peace Building di Bappenas untuk reintegrasi dan perdamaian Aceh. Tak heran jika ia sering bolak-balik Jakarta-Banda Aceh.
Dalam makalahnya, Kurnia Effendi menulis, bahwa pembicaraan tentang laut (dalam hal metafora, sebagai latar tempat, personifikasi, maupun esensi) sangat karib dalam puisi Dino. Boleh jadi ini menunjukkan kedekatan penyairnya dengan laut sebagai lingkungan yang membesarkan dan atau menjadi obsesinya. Sebagai orang Indonesia bagian Timur, tepatnya Ambon, sekaligus sebagai cucu dari moyang Nusantara yang konon para pelaut, sudah seharusnya manusia Indonesia memiliki “darah” kelautan.
Sementara Ikranegara, budayawan yang kini mukim di Amerika Serikat, dalam kata pengantar di buku tersebut mengatakan, bahwa puisi-puisi Dino lahir karena adanya kegalauan yang sangat manusiawi dalam menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dia alami sendiri; baik itu kejadian sosial politik, maupun yang terjadi atas diri pribadi.
Terlepas dari penilaian keduanya, kita berharap agar buku ini tidak lalu sekadar menjadi penanda kepenyairan seorang Dino Flores Umahuk, tetapi juga bisa ikut memberi kontribusi yang berarti bagi kekayaan ranah sastra Indonesia.***