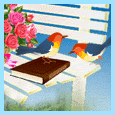AKU DAN SASTRA
Thursday, September 27, 2007,7:51 PM
 Maulana M.Syuhada
Maulana M.SyuhadaDENGAN ANGKLUNG ‘MENAKLUKKAN’ EROPA
Peristiwanya telah lama usai. Tepatnya terjadi di sepanjang bulan Juli-Agustus tiga tahun silam. Serombongan anak muda asal Kota Kembang yang bernaung di bawah Keluarga Paduan Angklung SMAN 3 Bandung (KPA 3), melangsungkan muhibah kesenian ke Eropa. Dengan niat mulia memperkenalkan musik tradisional Jawa Barat bernama angklung, ketiga puluh lima pemuda–25 siswa SMA serta 10 orang mahasiswa–ini sukses menggebrak panggung-panggung pertunjukan di enam negara Eropa (Belgia, Prancis, Inggris, Ceko, Polandia, dan Jerman) selama 40 hari.
Keberhasilan kontingen angklung tersebut tak bisa dilepaskan dari andil dan kerja keras Maulana M. Syuhada, seorang mahasiswa Indonesia yang tengah mengambil gelar master Manajemen Produksi di Technische Universitaet Hamburg-Haburg, Jerman. Keterlibatan total Maulana pada misi ini bukan hanya karena kesetiaan pada almamaternya, namun ada tujuan lebih besar lagi, yakni mengharumkan nama bangsa dan negara lewat kesenian dan kebudayaan.
“Di berbagai bidang, kita terpuruk di mata dunia. Hanya lewat kesenianlah kita masih bisa berbangga,” kata Maulana pada kesempatan Senin malam pekan lalu di toko buku MP Book Point, Jakarta. Pada waktu lain, lewat tayangan sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta nasional, lelaki berumur 30 tahun ini juga berujar tentang rasa nasionalismenya yang kian tumbuh subur justru setelah ia berada jauh dari tanah air.
Kendati belum pernah secara resmi menjadi anggota KPA 3, sejatinya Maulana adalah seorang pencinta seni yang hobi sekolah. Maka, setamatnya dari Teknik Industri ITB (2001), ia terbang ke Jerman, melanjutkan pendidikannya ke jenjang master. Selama tinggal di negeri Hitler ini, ia aktif terlibat di berbagai kegiatan seni dan budaya, hingga pada 2002 berhasil membentuk kelompok “Angklung-Orchester Hamburg” di kampusnya dengan anggota para mahasiswa asing yang berasal dari sepuluh negara.
Sepak terjangnya kemudian berlanjut dengan mendirikan grup Sabilulungan, yakni sebuah grup kesenian Sunda dengan spesialisasi kecapi-suling dan rampak gendang. Selain itu, ia pun turut tergabung dalam grup gamelan Margil Budoyo Hamburg serta merupakan salah seorang konseptor “wayang kontemporer” yang dipentaskan pertama kali di Eropa pada November 2003.
Dari seabreg kesibukannya menggeluti kesenian–khususnya kesenian Sunda–pengalaman terbesar, spektakular, dan tak akan pernah dilupakan seumur hidup adalah saat ia memimpin KPA 3 melakukan konser ke enam negara Eropa dalam rangka mengikuti tiga festival musik dan tari internasional selama 40 hari pada musim panas 2004. Dan, dengan bersenjatakan angklung itulah ia ‘menaklukkan’ Eropa.
Hasil gemilang yang telah diraih bukanlah jatuh begitu saja dari surga. Di baliknya ada sederet cerita muram tentang perjuangan seorang Maulana beserta adik-adik kelasnya itu. Mereka sempat ditolak oleh panitia penyelenggara Aberdeen Youth International Festival hanya 3 bulan menjelang hari “H”. Untunglah, berkat upaya dan kekuatan lobi masalah tersebut bisa diatasi.
Tetapi itu belum seberapa. Masih ada lagi yang lebih ekstrem dan menegangkan. Seminggu sebelum keberangkatan ke Eropa, perusahaan yang sedianya akan mensponsori, mendadak membatalkan kontrak secara sepihak. Kontan, seluruh rombongan lemas lunglai dan panik, tak tahu mesti bagaimana mengusahakan dana sebesar 300 juta rupiah. Di saat-saat kritis itu, Maulana tampil memberi semangat dan mencarikan jalan keluarnya.
Pendek kata, akhirnya mereka bisa berangkat walaupun dengan biaya yang serba minim hasil dari mengutang sana-sini termasuk berjualan CD (compact disk) berisi rekaman lagu-lagu mereka plus aneka cendera mata etnis dari Indonesia seperti wayang golek, batik, pulpen, dll.
Segala jerih payah mereka tak percuma. Di setiap penampilan mereka selalu diganjar sambutan dan apresiasi yang baik dari khalayak penonton. Bahkan ketika tampil sebagai bintang tamu di Festival Zakopane, Polandia, tanpa diduga mereka dianugerahi Ciupaga, yakni penghargaan tertinggi yang hanya diberikan kepada para pemenang kompetisi highland folklore, bukan kepada bintang tamu. Di sini, mereka juga memenangi audience award. Rupa-rupanya nomor “Jali-Jali” serta “Siksik Si Batu Manikam” yang mereka bawakan telah memikat hati para juri dan publik penonton. Sungguh prestasi yang membanggakan.
Seluruh pengalaman indah dan berkesan ini kemudian diabadikan Maulana dalam sebuah buku setebal 550 halaman berjudul 40 Days In Europe . Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bentang dan telah diluncurkan awal September lalu di Bandung.
Menurut Maulana pengalaman berharga ini patut dibagi kepada banyak orang agar dari situ orang lain dapat memetik hikmah dan pelajaran. Kandidat doktor yang harus segera kembali ke kampusnya di Inggris sana telah membuktikan, bahwa dengan kerja keras, doa, dan pertolongan-Nya, segala yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin.
Ide untuk membukukan perjalanan ESA (Expand the Sound of Angklung) ini, sebetulnya sudah muncul sejak petualangan 40 hari tersebut berakhir. Namun, karena kesibukan menyelesaikan studi, baru pada awal tahun ini ia berkesempatan menuliskannya. Itupun lantaran ia mesti istirahat total di ranjangnya selama empat bulan tersebab patah tulang kaki yang diperolehnya saat bermain sepak bola. “Andaikan kaki saya tidak pernah patah, mungkin buku ini tidak akan pernah ada”, katanya. Peristiwa tersebut semakin menambah keyakinannya bahwa di balik sebuah musibah pasti ada hikmahnya.***
Thursday, September 20, 2007,7:19 PM
 PEMENTASAN TEATER DAN DISKUSI NOVEL “JANDA DARI JIRAH”
PEMENTASAN TEATER DAN DISKUSI NOVEL “JANDA DARI JIRAH”Telah banyak kali cerita tentang Calon Arang ditulis dan dipentaskan. Legenda Tanah Bali yang terkait riwayat Raja Kediri, Airlangga, itu hampir selalu memghadirkan sosok Calon Arang dalam wujud fisik dan perangai yang buruk. Dalam banyak versi bahkan ia dihadirkan sebagai seorang nenek tua tukang teluh yang marah karena putrinya semata wayang, Ratna Manggali, tak juga ada yang kunjung meminang.
Namun, tidak demikian kiranya di tangan Cok Sawitri, penyair asal Bali yang juga dikenal sebagai artis teater. Dalam novel terbarunya, Cok menampilkan Calon Arang–ia menyebutnya “Rangda Ing Jirah”–dalam wujud wanita cantik, anggun, berilmu tinggi, berwibawa, dan seorang penganut Buddha yang taat. Novel tersebut, Janda dari Jirah, diluncurkan dan didiskusikan pada Rabu malam, 19 September 2007, di Goethehaus, Jakarta. Diskusi yang dipandu oleh Reda Gaudiamo itu mengundang Rieke Dyah Pitaloka (penulis, penyair, dan pemain sinetron) serta Maria Hartiningsih (junalis Kompas) sebagai pembahas.
Pada kesempatan tersebut, kedua wanita pembicara ini sepakat bahwa novel Janda dari Jirah merupakan karya fiksi yang menarik disimak dan dinikmati. Bukan saja lantaran bahasanya yang puitis tetapi juga karena dalam novel setebal 184 halaman tersebut, Cok Sawitri telah melakukan dekonstruksi terhadap citra Calon Arang yang kita kenal lewat dongeng-dongeng yang beredar selama ini.
Dari penuturan Maria Hartiningsih sebagai seorang yang dipercaya membaca draf kasar novel tersebut, Janda dari Jirah ditulis Cok Sawitri setelah melakukan penelitian selama tidak kurang dari sepuluh tahun. Banyak naskah kuno dan prasasti bersejarah yang dibaca dan dicermati Cok untuk novelnya ini. Cok yang selama ini lebih banyak menulis puisi ini juga telah menyambangi negeri Belanda guna memperoleh bahan-bahan penelitiannya. Janda dari Jirah hanyalah titik awal bagi sebuah karya yang lebih besar lagi. Sayangnya, sang penulis belum mau membagi rahasianya ikhwal karya besar tersebut. Tapi yang pasti, karya itu adalah sebuah buku.
Selain bedah buku, malam itu dipentaskan pula lakon Calon Arang berjudul “Dirah” oleh kelompok teater “Creamer Box” dan “Kendan”. Peretunjukan yang lebih banyak mempertontonkan gerak tubuh (tarian) ini terasa magis dan sakral, sebab konon para penarinya, termasuk Cok Sawitri yang memerankan Dirah, sebelum pertunjukan lebih dulu melaksanakan sejumlah ritual.
Sebelumnya, di tempat yang sama, telah pula dilangsungkan konferensi pers Ubud Writers & Readers Festival. Acara sastra tahunan ini akan digelar selama sepekan di Ubud, Bali mulai 25 September 2007 mendatang. Tahun ini, rencananya akan mendatangkan 100 penulis dari 18 negara, termasuk Indonesia***.
Endah Sulwesi 20/9
Friday, September 14, 2007,9:04 PM
 QARIS TAJUDIN: “Waktu kecil saya tidak boleh baca komik…”
QARIS TAJUDIN: “Waktu kecil saya tidak boleh baca komik…”Jika Anda penggemar fiksi lokal, barangkali tahu bahwa saat ini di pasar tengah beredar novel baru berjudul Mahasati. Novel bertema cinta tersebut ditulis oleh seorang penulis muda berbakat yang juga jurnalis. Dia adalah Qaris Tajudin. Saat ini menjabat sebagai redaktur mode dan gaya hidup di Koran Tempo. Pria berusia 33 tahun pada 13 Agustus yang lalu ini pada mulanya hanya bercita-cita menjadi wartawan. Ia tak pernah menyangka ketika akhirnya bisa menerbitkan sebuah karya fiksi berupa novel setebal hampir 400 halaman.
“Mahasati memang karya perdana yang saya harap bisa menjadi batu pijakan saya untuk melangkah lebih mantap lagi memasuki dunia penulisan fiksi,” kata Qaris menjelaskan arti penting karya debutannya itu. Sesungguhnya, ia telah lama jatuh cinta pada fiksi. Bermula di tahun 1986, saat pertama kali dia memiliki komputer sendiri. Waktu itu, Qaris masih seorang remaja baru lulus Sekolah Dasar di kampung halamannya di Bangil, Jawa Timur sana.
“Fiksi-fiksian,” demikian ia menyebut tulisan pertamanya berupa cerita berjenis thriller. Mengapa thriller? “Terpengaruh Lima Sekawan. Ha..ha..ha,” Qaris tertawa renyah mengenang kembali masa-masa awalnya berkenalan dengan dunia tulis-menulis. “Tapi waktu kecil saya nggak boleh baca komik, lho. Makanya, saya terlambat mengenal Donald Bebek”. Satu-satunya komik yang boleh dilahap penggemar novel-novel Murakami dan J.D. Salinger ini adalah Mahabarata-nya R.A. Kosasih. Itupun lantaran sang bunda tercinta kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan Qaris kecil setiap usai menonton pertunjukan wayang di TVRI. “Jadi saya disuruh baca sendiri saja di komik itu. He..he..he,” Qaris terkekeh saat membongkar kembali memori masa kecilnya.
Berikutnya, ia melewatkan masa SMP dan SMA di sebuah pesantren milik Persatuan Islam (Persis) di Bangil sebelum akhirnya terbang jauh ke Kairo, Mesir, demi mereguk ilmu filsafat di universitas paling bergengsi di sana: Al Azhar. Enam tahun dia menempuh kuliah untuk kemudian mengawali karier idamannya sebagai jurnalis hingga hari ini.
Nama Qaris sendiri memiliki makna “dingin sekali”. Diambil dari kosa kata bahasa Arab. Tetapi siapa menyangka jika ternyata ia justru keturunan India. “Ayah saya, India. Ibu saya dari Malang,” jelas anak ketiga dari lima bersaudara ini. Pengagum berat Goenawan Muhammad dan Nizar Qabbani ini juga menggeluti puisi, meskipun belum berniat untuk menerbitkannya dalam sebuah buku. Sementara ini, puisi-puisi karyanya baru bisa diintip di blog miliknya: www.cerminretak.blogdrive.com.
Lelaki yang menikah pada 2003 dengan seorang perempuan bernama Fardiah ini, selanjutnya mengisahkan tentang pengalaman “berdarah-darah”-nya selama menyelesaikan Mahasati. Dari mulai penulisan hingga diterbitkan, seluruhnya memakan waktu lima tahun. Sebuah penantian yang cukup panjang. Kendati begitu, Qaris tak lalu jadi kapok. Ia malah ketagihan. “Saya bahkan sudah mulai menulis (calon) novel kedua saya,” ujarnya berbagi rahasia. Namun, ia tak hendak membocorkan dulu bercerita tentang apa novel keduanya kelak. “Tunggu saja nanti ya,” katanya sembari mengulum senyum, “Pokoknya masih tentang cinta”.
Ah..mengapa mesti (tentang) cinta lagi, Qaris? “Ya..sebab kalau bukan cinta, kayaknya buku saya bakal jadi cerita yang gelap dan kelam,” tandasnya. Ia yakin, lewat (kisah) cinta (dengan berbagai variasinya) segala hal bisa disampaikan.
Di Koran Tempo, Qaris juga terlibat dalam sidang redaksi Ruang Baca; suplemen khusus sastra yang terbit rutin satu bulan sekali pada setiap pekan ketiga. Untuk itu, mau tidak mau ia harus rajin mengamati perkembangan sastra. Menurutnya, dinamika sastra tanah air cukup menggembirakan jika dilihat dari banyak lahirnya para penulis muda. Hal tersebut dimungkinkan oleh situasi hari ini yang sangat kondusif bagi siapapun untuk menulis. Perkara mutu, biarlah diurus belakangan. Yang penting jadikan dulu menulis (dan membaca) sebagai budaya. Ia juga menyambut gembira buku-buku sastra terjemahan yang belakangan tumbuh menjamur memenuhi rak di toko-toko buku kita. Tak perlu cemas dengan buku-buku impor itu, justru jadikan itu sebagai pemacu motivasi.
Kembali bercerita ihwal karier jurnalistiknya, Qaris sangat terkesan dengan pengalamannya meliput langsung perang terbuka di Afganistan (2001). “Suvenir” dari medan tempur itulah yang lantas diabadikan dalam Mahasati. Banyak yang “curiga”, bahwa tokoh Andi Jatmika dalam Mahasati merupakan alter ego dirinya. “Mungkin ya. Biasa deh, karya pertama biasanya kan lebih gampang mengambil model hal-hal yang akrab dengan kita,” sahutnya lugas. “Untuk fiksi, saya memilih menulis hal-hal realis yang dikemas dengan bahasa sehari-hari yang ringan tanpa terjerumus menjadi chicklit”.
Intinya, Qaris Tajudin akan terus menulis fiksi sambil tetap menekuni karier kewartawanannya, sebab ia sadar betul bahwa pilihan (menjadi penulis) itu belum bisa dijadikan sumber nafkah yang memadai.***
Biodata singkat:
Nama lengkap: Qaris Tajudin
Tempat/tgl.lahir: Bangil, 13 Agustus 1974.
Nama istri: Fardiah
Nama ayah/ibu: Tajudin (alm)/Sri Hartati
Pendidikan: Jurusan Filsafat Univervitas Al Azhar, Mesir.
Pekerjaan: Redaktur Mode dan Gaya Hidup Koran Tempo
ENDAH SULWESI