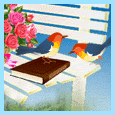AKU DAN SASTRA
Tuesday, February 26, 2008,10:12 PM
 "SIDANG SUSILA" TEATER GANDRIK
"SIDANG SUSILA" TEATER GANDRIKTeater Gandrik dan Butet Kartaredjasa seperti kembar siam yang tidak terpisahkan. Sejak berdirinya pada 12 September 1983 mereka selalu bersama, bagaikan sepasang kekasih yang saling setia. Di mana ada pentas Gandrik, di situ berarti ada Butet. Teater asal Yogyakarta ini terakhir kali manggung tahun 2003, mengusung lakon Departemen Borok. Setelah vakum lima tahun mereka kembali mentas di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta selama dua malam (22-23 Februari 2008).
Sebagaimana galibnya pementasan Gandrik yang sudah-sudah, kali ini pun teater tersebut masih percaya pada kekuatan gaya sampakan yang meniadakan batas antara “aktor sebagai pemain” dengan “watak yang dimainkannya”. Model permainan seperti ini juga sangat membuka peluang bagi para pemain melakukan improvisasi dan bahkan kadang-kadang melibatkan penonton. Pola sampakan ini diadaptasi oleh Gandrik dari banyak kecenderungan di teater tradisional Tanah Air. Misalnya saja, lenong Betawi atau ludruk Jawa Timuran.
Setiap aktor boleh bermain sebagai lelaki atau perempuan tanpa terjerumus menjadi banyolan banci-bancian yang slapstick. Seperti kali ini, dalam lakon Sidang Susila karya kolaborasi Ayu Utami dan Agus Noor, Butet kebagian peran perempuan pengacara (pembela). Dalam balutan kostum dan tata rias bernuansa Bali, “Raja Monolog” ini tampil kenes dalam perannya tersebut beradu akting dengan aktor lainnya yang juga memerankan karakter perempuan, Whani Darmawan.
Tentu saja naskah yang mereka pentaskan masih sarat dengan kritik sosial. Sidang Susila sejatinya ingin merespons dan menyikapi RUU Tentang Pornografi yang baru saja selesai digarap DPR dan telah diserahkan kepada pemerintah untuk disahkan. Dalam Undang-undang ini memuat segala peraturan ikhwal perbuatan dan perilaku masyarakat yang berkenaan dengan pornografi. Celakanya, menurut Ayu Utami, RUU tersebut memperlakukan kesenian, kebudayaan, dan adat istiadat sejajar dengan sekadar pengobatan disfungsi ereksi.
Lebih jelasnya, penulis novel Saman ini mengambil contoh pasal 8 RUU itu yang melarang orang menggunakan anak sebagai obyek atau model pornografi. Namun, di pasal 13, ada pengecualian: Larangan-larangan (tersebut)….tidak meliputi pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi untuk tujuan a) pengobatan gangguan kesehatan seksual, b) pertunjukan seni dan budaya, c) adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual.
Di panggung Gandrik, lakon Sidang Susila disajikan dalam kemasan komedi cerdas dan segar yang terkesan main-main, mengundang gelak tawa penonton yang malam itu (22/2) memenuhi seluruh kursi. Malah sebagaian ada yang rela membeli tiket “lesehan”.
Kisahnya adalah tentang Susila Parna (Susilo Nugroho), seorang pedagang mainan anak-anak yang sial terkena razia polisi susila. Tuduhan kepada lelaki berbuah dada big size ini adalah karena ia telah mempertontonkan tubuhnya di sebuah pesta tayuban. Maka, ia pun harus disidang untuk mempertaggungjawabkan perbuatannya yang dianggap asusila itu.
Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim (Heru Kesawa Murti) serta Jaksa (Whani Darmawan) itu mendakwa Susila dengan pasal berlapis-lapis sehingga Pembelanya (Butet Kartaredjasa) kesulitan memberikan advokasi. Sementara itu publik di luar ruang pengadilan ribut berdemo, sebagian menuntut Susila dihukum sesuai perbuatannya dan yang lain menyerukan tuntutan untuk membebaskan tukang mainan itu dari segala tuduhan. Ada juga kelompok dan pihak-pihak yang berusaha menangguk keuntungan dari kasus Susila ini. Semuanya merupakan gambaran riil yang terjadi di masyarakat kita.
Uniknya, pertunjukan ini disutradarai oleh sebuah tim yang terdiri dari para pemain dan semua yang terlibat di dalamnya. Hal ini berangkat dari situasi selama latihan yang berkembang setiap waktu; melahirkan gagasan-gagasan baru bagi pementasan tersebut. Ide semula yang ingin menunjuk seseorang sebagai dalang menjadi tidak relevan lagi lantaran pada kenyataannya peran sutradara itu dikerjakan secara keroyokan. Singkatnya, sutradaranya adalah Teater Gandrik. Adapun urusan musik masih tetap dipercayakan pada Djaduk Ferianto yang juga berperan sebagai Kepala Keamanan.
Jika ukuran sukses sebuah pertunjukan dilihat dari tiket yang terjual, maka pentas Gandrik pekan lalu terhitung sukses. Berikutnya, mereka akan menggelar Sidang Susila di Taman Budaya Yogyakarta pada 7 dan 8 Maret yang akan datang. ***ENDAH SULWESI
Sebagaimana galibnya pementasan Gandrik yang sudah-sudah, kali ini pun teater tersebut masih percaya pada kekuatan gaya sampakan yang meniadakan batas antara “aktor sebagai pemain” dengan “watak yang dimainkannya”. Model permainan seperti ini juga sangat membuka peluang bagi para pemain melakukan improvisasi dan bahkan kadang-kadang melibatkan penonton. Pola sampakan ini diadaptasi oleh Gandrik dari banyak kecenderungan di teater tradisional Tanah Air. Misalnya saja, lenong Betawi atau ludruk Jawa Timuran.
Setiap aktor boleh bermain sebagai lelaki atau perempuan tanpa terjerumus menjadi banyolan banci-bancian yang slapstick. Seperti kali ini, dalam lakon Sidang Susila karya kolaborasi Ayu Utami dan Agus Noor, Butet kebagian peran perempuan pengacara (pembela). Dalam balutan kostum dan tata rias bernuansa Bali, “Raja Monolog” ini tampil kenes dalam perannya tersebut beradu akting dengan aktor lainnya yang juga memerankan karakter perempuan, Whani Darmawan.
Tentu saja naskah yang mereka pentaskan masih sarat dengan kritik sosial. Sidang Susila sejatinya ingin merespons dan menyikapi RUU Tentang Pornografi yang baru saja selesai digarap DPR dan telah diserahkan kepada pemerintah untuk disahkan. Dalam Undang-undang ini memuat segala peraturan ikhwal perbuatan dan perilaku masyarakat yang berkenaan dengan pornografi. Celakanya, menurut Ayu Utami, RUU tersebut memperlakukan kesenian, kebudayaan, dan adat istiadat sejajar dengan sekadar pengobatan disfungsi ereksi.
Lebih jelasnya, penulis novel Saman ini mengambil contoh pasal 8 RUU itu yang melarang orang menggunakan anak sebagai obyek atau model pornografi. Namun, di pasal 13, ada pengecualian: Larangan-larangan (tersebut)….tidak meliputi pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi untuk tujuan a) pengobatan gangguan kesehatan seksual, b) pertunjukan seni dan budaya, c) adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual.
Di panggung Gandrik, lakon Sidang Susila disajikan dalam kemasan komedi cerdas dan segar yang terkesan main-main, mengundang gelak tawa penonton yang malam itu (22/2) memenuhi seluruh kursi. Malah sebagaian ada yang rela membeli tiket “lesehan”.
Kisahnya adalah tentang Susila Parna (Susilo Nugroho), seorang pedagang mainan anak-anak yang sial terkena razia polisi susila. Tuduhan kepada lelaki berbuah dada big size ini adalah karena ia telah mempertontonkan tubuhnya di sebuah pesta tayuban. Maka, ia pun harus disidang untuk mempertaggungjawabkan perbuatannya yang dianggap asusila itu.
Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim (Heru Kesawa Murti) serta Jaksa (Whani Darmawan) itu mendakwa Susila dengan pasal berlapis-lapis sehingga Pembelanya (Butet Kartaredjasa) kesulitan memberikan advokasi. Sementara itu publik di luar ruang pengadilan ribut berdemo, sebagian menuntut Susila dihukum sesuai perbuatannya dan yang lain menyerukan tuntutan untuk membebaskan tukang mainan itu dari segala tuduhan. Ada juga kelompok dan pihak-pihak yang berusaha menangguk keuntungan dari kasus Susila ini. Semuanya merupakan gambaran riil yang terjadi di masyarakat kita.
Uniknya, pertunjukan ini disutradarai oleh sebuah tim yang terdiri dari para pemain dan semua yang terlibat di dalamnya. Hal ini berangkat dari situasi selama latihan yang berkembang setiap waktu; melahirkan gagasan-gagasan baru bagi pementasan tersebut. Ide semula yang ingin menunjuk seseorang sebagai dalang menjadi tidak relevan lagi lantaran pada kenyataannya peran sutradara itu dikerjakan secara keroyokan. Singkatnya, sutradaranya adalah Teater Gandrik. Adapun urusan musik masih tetap dipercayakan pada Djaduk Ferianto yang juga berperan sebagai Kepala Keamanan.
Jika ukuran sukses sebuah pertunjukan dilihat dari tiket yang terjual, maka pentas Gandrik pekan lalu terhitung sukses. Berikutnya, mereka akan menggelar Sidang Susila di Taman Budaya Yogyakarta pada 7 dan 8 Maret yang akan datang. ***ENDAH SULWESI
Friday, February 15, 2008,10:56 PM
 MERAYAKAN CINTA BERSAMA SAPARDI
MERAYAKAN CINTA BERSAMA SAPARDIEntah disengaja atau tidak, pada tanggal 14 Februari 2008 bertepatan dengan hari yang dikenal sebagai Valentine’s Day, digelar acara pembacaan dan musikalisasi puisi-puisi cinta Sapardi Djoko Damono. Tak kurang dari dua puluhan sajak cinta dibawakan oleh sejumlah seniman di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Acara yang berlangsung selama dua malam berturut-turut ini menampilkan duet Ari-Reda, Jose Rizal Manua, Teater Tanah Air, Kelompok Paduan Suara Gita Swara Nassa, Lab. Musik Jakarta, Teater Tetas, Ags. Arya Dipayana, Cornelia Agatha, dan Ine Febriyanti.
Mereka secara bergantian mengusung puisi-puisi karya penyair gaek yang juga adalah guru besar dan kritikus sastra handal itu dalam bentuk pembacaan, teater, dan musikalisasi. Mengalunlah dengan indah dan syahdu di atas panggung untaian bait-bait cinta yang beberapa telah sangat akrab bagi para pencinta Sapardi dan Ari-Reda. Nomor-nomor beken seperti “Aku Ingin”, “Hujan Bulan Juni”, “Dalam Dirimu, “Nokturno”, “Di Restoran”, dan “Pada Suatu Hari Nanti” disenandungkan dalam nada-nada bening vokal Reda Gaudiamo yang kadang tinggi melengking dipadu suara manis Ari Malibu dengan iringan petikan gitar akustiknya. Keindahan duet itu tambah memukau tatkala maestro gitar, Jubing Kristanto, “turut campur” dalam nomor “Gadis Kecil” dan “Aku Ingin”.
Tak pelak lagi, malam itu duo Ari-Reda adalah bintang panggung yang dinanti-nanti penonton. Meski sebagian kursi terlihat kosong, namun tak mengurangi semangat mereka untuk memberikan penampilan terbaik. Sayangnya, penempatan perangkat lighting tepat di tengah-tengah panggung bagian depan, terasa sangat tidak pas dan mengganggu pemandangan ke atas pentas, terutama untuk hadirin yang duduk di kursi barisan depan. Bahkan ketika kelompok Lab. Musik Jakarta tampil, penonton di deret depan sama sekali tidak bisa melihat mereka lantaran terhalang oleh benda yang salah letak tersebut. Selebihnya, pertunjukan pada malam yang diguyur rinai gerimis tanpa henti itu, terbilang sukses. Antusias penonton pada setiap penampil cukup meriah. Rasanya akan bertambah seru andai para pengunjung malam itu bisa lebih ekspresif lagi dengan ikut serta berdendang bersama, seperti pada pertunjukan musik umumnya.
Pada kesempatan itu, sang empunya sajak turut didaulat pula untuk membacakan karyanya. Maka, ia pun beraksi dengan satu puisinya: “Hujan dalam Komposisi”. Dalam kurun waktu lebih dari empat puluh tahun kiprahnya, Sapardi telah mengabadikan karya-karyanya dalam beberapa buku kumpulan puisi, seperti Dukamu Abadi (1969), Mata Pisau (1974), Perahu Kertas (1983), Sihir Hujan (1984), Hujan Bulan Juni (1994), dan Ayat-ayat Api (2000). Kini, di usianya yang kian senja (lahir 20 Maret 1940), ia masih aktif berkarya, tanpa henti terus mencari kemungkinan atas kata. Sajak-sajak cintanya laksana mantra yang menyihir banyak orang. Bagaikan dua orang yang saling mencinta, begitulah Sapardi dan puisi : tak akan pernah terpisahkan. ***ENDAH SULWESI
Mereka secara bergantian mengusung puisi-puisi karya penyair gaek yang juga adalah guru besar dan kritikus sastra handal itu dalam bentuk pembacaan, teater, dan musikalisasi. Mengalunlah dengan indah dan syahdu di atas panggung untaian bait-bait cinta yang beberapa telah sangat akrab bagi para pencinta Sapardi dan Ari-Reda. Nomor-nomor beken seperti “Aku Ingin”, “Hujan Bulan Juni”, “Dalam Dirimu, “Nokturno”, “Di Restoran”, dan “Pada Suatu Hari Nanti” disenandungkan dalam nada-nada bening vokal Reda Gaudiamo yang kadang tinggi melengking dipadu suara manis Ari Malibu dengan iringan petikan gitar akustiknya. Keindahan duet itu tambah memukau tatkala maestro gitar, Jubing Kristanto, “turut campur” dalam nomor “Gadis Kecil” dan “Aku Ingin”.
Tak pelak lagi, malam itu duo Ari-Reda adalah bintang panggung yang dinanti-nanti penonton. Meski sebagian kursi terlihat kosong, namun tak mengurangi semangat mereka untuk memberikan penampilan terbaik. Sayangnya, penempatan perangkat lighting tepat di tengah-tengah panggung bagian depan, terasa sangat tidak pas dan mengganggu pemandangan ke atas pentas, terutama untuk hadirin yang duduk di kursi barisan depan. Bahkan ketika kelompok Lab. Musik Jakarta tampil, penonton di deret depan sama sekali tidak bisa melihat mereka lantaran terhalang oleh benda yang salah letak tersebut. Selebihnya, pertunjukan pada malam yang diguyur rinai gerimis tanpa henti itu, terbilang sukses. Antusias penonton pada setiap penampil cukup meriah. Rasanya akan bertambah seru andai para pengunjung malam itu bisa lebih ekspresif lagi dengan ikut serta berdendang bersama, seperti pada pertunjukan musik umumnya.
Pada kesempatan itu, sang empunya sajak turut didaulat pula untuk membacakan karyanya. Maka, ia pun beraksi dengan satu puisinya: “Hujan dalam Komposisi”. Dalam kurun waktu lebih dari empat puluh tahun kiprahnya, Sapardi telah mengabadikan karya-karyanya dalam beberapa buku kumpulan puisi, seperti Dukamu Abadi (1969), Mata Pisau (1974), Perahu Kertas (1983), Sihir Hujan (1984), Hujan Bulan Juni (1994), dan Ayat-ayat Api (2000). Kini, di usianya yang kian senja (lahir 20 Maret 1940), ia masih aktif berkarya, tanpa henti terus mencari kemungkinan atas kata. Sajak-sajak cintanya laksana mantra yang menyihir banyak orang. Bagaikan dua orang yang saling mencinta, begitulah Sapardi dan puisi : tak akan pernah terpisahkan. ***ENDAH SULWESI
Friday, February 08, 2008,10:29 PM
 QAISRA SHAHRAZ: “Bagi saya kesetaraan itu penting.”
QAISRA SHAHRAZ: “Bagi saya kesetaraan itu penting.”Selasa pagi menjelang siang, 5 Februari 2008, Qaisra Shahraz bersama suami dan Pangestuningsih dari Penerbit Mizan, tiba di Perkebunan Teh Gunung Mas. Bukan kunjungan resmi, hanya mampir untuk minum teh sembari istirahat di tengah-tengah jadwalnya yang padat sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandung. Qaisra berada di Indonesia sepekan lebih untuk mempromosikan kedua novelnya yang telah terbit, yakni The Holy Woman (2001) dan Typhoon (2003). Terjemahan Indonesianya menjadi Perempuan Suci dan Perempuan Terluka, diterbitkan oleh Mizan.
Selama di Indonesia–ini merupakan kedatangannya yang kedua–wanita kelahiran Pakistan dan besar di Inggris ini mengadakan serangkaian acara diskusi buku, jumpa penggemar, dan wawancara di sejumlah kota besar di Jawa (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya). Siang itu, ia mengenakan busana muslimah berupa tunik coklat bermotif bordir dipadu celana panjang dan selembar kerudung hitam yang disampirkan di lehernya.
Pada kunjungan tersebut Qaisra tak sekadar menikmati kehangatan secangkir teh Walini saja, namun juga dipergunakannya untuk bercakap-cakap dengan sejumlah perempuan pekerja pabrik dan pemetik teh. Penulis yang pernah meraih Jubilee Award (2003) ini mengungkapkan, bahwa ia ingin bicara dengan banyak orang di seluruh dunia, terutama para perempuannya. Saya sungguh beruntung memperoleh kesempatan ngobrol dengan novelis cantik ini.
Riwayat kepenulisannya dimulai sejak ia berumur 19 tahun. Sebenarnya pada umur 14 tahun pun ia telah senang menulis. Kariernya dimulai sebagai jurnalis koran dan majalah sebelum kemudian membuat cerita pendek dan novel. “Dan saya telah menulis selama 23 tahun,” ujar Qaisra seraya mengaduk teh di cangkirnya. Saat ini ia tengah menyelesaikan novel ketiganya.
“Kepedulian saya pada hubungan antarmanusia, tetapi fokus utama saya perempuan,” Qaisra menjawab pertanyaan seputar kedua karyanya yang mengangkat persoalan perempuan di Pakistan, “Saya tertarik pada kehidupan mereka, pada yang mereka lakukan.” Dan itu tidak terbatas pada perempuan Pakistan saja, namun di seluruh dunia.
Menurut sarjana lulusan Universitas Manchester ini persoalan perempuan di dunia yang paling mengkhawatirkan adalah kesehatan. Pendidikan memang penting, tetapi kesehatan jauh lebih penting. Masih banyak perempuan di dunia ini yang tidak memiliki akses ke dokter, terutama saat hamil dan melahirkan yang dapat mengakibatkan kematian.
Dan Qaisra merasa sangat bersyukur sebab ia tinggal di Inggris yang memperlakukan para wanita dengan lebih baik dibandingkan tanah kelahirannya, Pakistan. “Ayah saya seorang sarjana dan punya pekerjaan serta latar belakang yang baik, saya beruntung sekali,” tutur Qaisra, “ tetapi jika saya tinggal di desa barangkali saya akan memiliki gaya hidup yang sangat berbeda.”
Namun dari semua, kata Qaisra dengan nada prihatin, kunci utamanya adalah masalah ekonomi. Bagaimana mau sekolah atau berobat ke dokter jika untuk makan saja sudah sulit. Kondisi ini menyebabkan para wanita terpaksa bekerja (kasar) mencari nafkah membantu suami meski harus meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Tetapi andai para wanita ini berpendidikan tinggi, tentu keadaannya akan berbeda. Pendidikan akan menghindarkan mereka dari “perangkap” itu. “Saya sangat berharap wanita-wanita itu mendapat kesempatan yang sama seperti yang kita lakukan, dan bagi saya kesetaraan itu penting.”
Lantas, apa yang paling mengesankannya selama di Indonesia? “For me, it is especially wise people, lovely charming people,” sahut Qaisra dengan senyum lebarnya,” I don’t understand it fully, but that is the word I usually use to describe it. And I love it. That’s why I come back again.”
Saat jarum jam mendekati pukul 14, Qaisra beserta rombongan mohon diri. Sebelum benar-benar meninggalkan Gunung Mas, ia masih meluangkan waktu berbincang sejenak dan berfoto bersama ibu-ibu pemetik teh. ***
Penghargaan yang pernah diterima Qaisra Shahraz:
Selama di Indonesia–ini merupakan kedatangannya yang kedua–wanita kelahiran Pakistan dan besar di Inggris ini mengadakan serangkaian acara diskusi buku, jumpa penggemar, dan wawancara di sejumlah kota besar di Jawa (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya). Siang itu, ia mengenakan busana muslimah berupa tunik coklat bermotif bordir dipadu celana panjang dan selembar kerudung hitam yang disampirkan di lehernya.
Pada kunjungan tersebut Qaisra tak sekadar menikmati kehangatan secangkir teh Walini saja, namun juga dipergunakannya untuk bercakap-cakap dengan sejumlah perempuan pekerja pabrik dan pemetik teh. Penulis yang pernah meraih Jubilee Award (2003) ini mengungkapkan, bahwa ia ingin bicara dengan banyak orang di seluruh dunia, terutama para perempuannya. Saya sungguh beruntung memperoleh kesempatan ngobrol dengan novelis cantik ini.
Riwayat kepenulisannya dimulai sejak ia berumur 19 tahun. Sebenarnya pada umur 14 tahun pun ia telah senang menulis. Kariernya dimulai sebagai jurnalis koran dan majalah sebelum kemudian membuat cerita pendek dan novel. “Dan saya telah menulis selama 23 tahun,” ujar Qaisra seraya mengaduk teh di cangkirnya. Saat ini ia tengah menyelesaikan novel ketiganya.
“Kepedulian saya pada hubungan antarmanusia, tetapi fokus utama saya perempuan,” Qaisra menjawab pertanyaan seputar kedua karyanya yang mengangkat persoalan perempuan di Pakistan, “Saya tertarik pada kehidupan mereka, pada yang mereka lakukan.” Dan itu tidak terbatas pada perempuan Pakistan saja, namun di seluruh dunia.
Menurut sarjana lulusan Universitas Manchester ini persoalan perempuan di dunia yang paling mengkhawatirkan adalah kesehatan. Pendidikan memang penting, tetapi kesehatan jauh lebih penting. Masih banyak perempuan di dunia ini yang tidak memiliki akses ke dokter, terutama saat hamil dan melahirkan yang dapat mengakibatkan kematian.
Dan Qaisra merasa sangat bersyukur sebab ia tinggal di Inggris yang memperlakukan para wanita dengan lebih baik dibandingkan tanah kelahirannya, Pakistan. “Ayah saya seorang sarjana dan punya pekerjaan serta latar belakang yang baik, saya beruntung sekali,” tutur Qaisra, “ tetapi jika saya tinggal di desa barangkali saya akan memiliki gaya hidup yang sangat berbeda.”
Namun dari semua, kata Qaisra dengan nada prihatin, kunci utamanya adalah masalah ekonomi. Bagaimana mau sekolah atau berobat ke dokter jika untuk makan saja sudah sulit. Kondisi ini menyebabkan para wanita terpaksa bekerja (kasar) mencari nafkah membantu suami meski harus meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Tetapi andai para wanita ini berpendidikan tinggi, tentu keadaannya akan berbeda. Pendidikan akan menghindarkan mereka dari “perangkap” itu. “Saya sangat berharap wanita-wanita itu mendapat kesempatan yang sama seperti yang kita lakukan, dan bagi saya kesetaraan itu penting.”
Lantas, apa yang paling mengesankannya selama di Indonesia? “For me, it is especially wise people, lovely charming people,” sahut Qaisra dengan senyum lebarnya,” I don’t understand it fully, but that is the word I usually use to describe it. And I love it. That’s why I come back again.”
Saat jarum jam mendekati pukul 14, Qaisra beserta rombongan mohon diri. Sebelum benar-benar meninggalkan Gunung Mas, ia masih meluangkan waktu berbincang sejenak dan berfoto bersama ibu-ibu pemetik teh. ***
Penghargaan yang pernah diterima Qaisra Shahraz:
Ian St. James Award (1994)
Jubilee Award (2003)
Pakistan Television Award (2004)
endah sulwesi 8/2