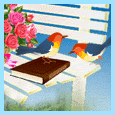AKU DAN SASTRA
Monday, May 29, 2006,1:44 PM
 Bencana Itu...
Bencana Itu...Jakarta, 27 Mei 2006
Sabtu pagi, pukul 6:46
Telepon selularku bergetar dengan bunyi pertanda pesan masuk. Dari penyairku : Joko Pinurbo. Ia mengabarkan Yogya berantakan, baru saja disambangi gempa. Rumah-rumah rubuh. Ada korban. Sementara, ia dan keluarganya baik-baik saja. Guncangan 5,9 pada skala Richter itu "hanya" membuat isi rumahnya berantakan serta beberapa lembar genting berjatuhan.
Aku mengira gempa tersebut cuma gempa yang biasa terjadi : tidak menimbulkan kerusakan dan korban serius. Apa lagi saat itu aku sedang dalam perjalanan ke kantor, di tol Jagorawi, di atas bus jurusan Sukabumi tak bisa langsung melihat siaran berita tv.
Namun, tak urung aku segera mengontak Kris, Ang Tek Khun, Diah, dan WD Yoga. Mereka adalah para sahabat yang berdomisili di Yogya. Balasan tercepat kuterima dari Kris. Ia meneleponku, menceritakan sedikit gambaran tentang gempa tersebut yang ber-episentrum di Samudra Hindia, 37 km dari pusat kota Yogyakarta. Alhamdulillah, Kris dan keluarga baik-baik saja.
Beberap saat kemudian, balasan dari Ang Tek Khun datang. Syukur, ia pun sehat wal afiat. Hanya masih terguncang oleh peristiwa tadi dan belum berani masuk rumah kembali, khawatir ada gempa susulan dan isu-isu tsunami yang membuat panik.
Sesampai di kantor, berita duka menyambutku : rumah mertua bosku hancur akibat gempa. Bosku sibuk mengontak kerabatnya yang lain namun belum juga berhasil. Sementara itu, televisi telah setiap satu jam sekali menayangkan perkembangan situasi dari lokasi kejadian. Jumlah korban yang dilaporkan setiap saat bertambah banyak saja hingga menjelang tengah hari telah mencapai angka 1300-an. Allahu Akbar! Aku benar-benar terpana. Tak mengira. Sungguh, ini bencana (lagi)!
Kemudian berita dari WD Yoga masuk. Terima kasih Tuhan, ia pun selamat. Ia kesulitan menghubungi teman-teman dan keluarganya sebab jaringan komunikasi terhambat dan aliran listrik mati.
Lalu, aku teringat Susan (Sannie B.Kuncoro) di Solo. Bagaimana ia? Di tv memang hanya menyebut Yogya. Tetapi, bukankan Solo hanya sepelemparan batu dari Yogya. Sannie balas menelponku dari Solo. Lagi-lagi aku merasa lega, karena iapun tak kurang suatu apa. Hanya masih tersisa gemetar dan kecemasan dalam suaranya. Ia bilang, pada saat gempa itu seperti sedang naik kapal laut yang digoyang ombak.
Petang hari, jumlah korban jiwa yang dilaporkan televisi telah menyentuh angka ribuan dengan korban terbanyak terdapat di Bantul, daerah yang hanya berjarak sekitar 7 km dari pusat gempa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku sedih.
Malam hari Puncak diguyur hujan deras disertai petir menggelegar membelah langit hitam. Aku mencemaskan semua mereka yang di Yogya. Diam-diam aku berdoa semoga hujan tak turun di Yogya agar mereka tak tambah menderita. Dan semoga tak ada lagi gempa susulan. Semoga malam berlalu dengan tenang.
Jakarta, 29 Mei 2006
Kini, tiga hari sudah gempa berlalu, menyisakan trauma, kesedihan, kepedihan, derita, malapetaka, dan juga cinta. Semoga segala duka cepat berlalu. Semoga kita diberi kesabaran dan ketabahan.
Sabtu pagi, pukul 6:46
Telepon selularku bergetar dengan bunyi pertanda pesan masuk. Dari penyairku : Joko Pinurbo. Ia mengabarkan Yogya berantakan, baru saja disambangi gempa. Rumah-rumah rubuh. Ada korban. Sementara, ia dan keluarganya baik-baik saja. Guncangan 5,9 pada skala Richter itu "hanya" membuat isi rumahnya berantakan serta beberapa lembar genting berjatuhan.
Aku mengira gempa tersebut cuma gempa yang biasa terjadi : tidak menimbulkan kerusakan dan korban serius. Apa lagi saat itu aku sedang dalam perjalanan ke kantor, di tol Jagorawi, di atas bus jurusan Sukabumi tak bisa langsung melihat siaran berita tv.
Namun, tak urung aku segera mengontak Kris, Ang Tek Khun, Diah, dan WD Yoga. Mereka adalah para sahabat yang berdomisili di Yogya. Balasan tercepat kuterima dari Kris. Ia meneleponku, menceritakan sedikit gambaran tentang gempa tersebut yang ber-episentrum di Samudra Hindia, 37 km dari pusat kota Yogyakarta. Alhamdulillah, Kris dan keluarga baik-baik saja.
Beberap saat kemudian, balasan dari Ang Tek Khun datang. Syukur, ia pun sehat wal afiat. Hanya masih terguncang oleh peristiwa tadi dan belum berani masuk rumah kembali, khawatir ada gempa susulan dan isu-isu tsunami yang membuat panik.
Sesampai di kantor, berita duka menyambutku : rumah mertua bosku hancur akibat gempa. Bosku sibuk mengontak kerabatnya yang lain namun belum juga berhasil. Sementara itu, televisi telah setiap satu jam sekali menayangkan perkembangan situasi dari lokasi kejadian. Jumlah korban yang dilaporkan setiap saat bertambah banyak saja hingga menjelang tengah hari telah mencapai angka 1300-an. Allahu Akbar! Aku benar-benar terpana. Tak mengira. Sungguh, ini bencana (lagi)!
Kemudian berita dari WD Yoga masuk. Terima kasih Tuhan, ia pun selamat. Ia kesulitan menghubungi teman-teman dan keluarganya sebab jaringan komunikasi terhambat dan aliran listrik mati.
Lalu, aku teringat Susan (Sannie B.Kuncoro) di Solo. Bagaimana ia? Di tv memang hanya menyebut Yogya. Tetapi, bukankan Solo hanya sepelemparan batu dari Yogya. Sannie balas menelponku dari Solo. Lagi-lagi aku merasa lega, karena iapun tak kurang suatu apa. Hanya masih tersisa gemetar dan kecemasan dalam suaranya. Ia bilang, pada saat gempa itu seperti sedang naik kapal laut yang digoyang ombak.
Petang hari, jumlah korban jiwa yang dilaporkan televisi telah menyentuh angka ribuan dengan korban terbanyak terdapat di Bantul, daerah yang hanya berjarak sekitar 7 km dari pusat gempa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku sedih.
Malam hari Puncak diguyur hujan deras disertai petir menggelegar membelah langit hitam. Aku mencemaskan semua mereka yang di Yogya. Diam-diam aku berdoa semoga hujan tak turun di Yogya agar mereka tak tambah menderita. Dan semoga tak ada lagi gempa susulan. Semoga malam berlalu dengan tenang.
Jakarta, 29 Mei 2006
Kini, tiga hari sudah gempa berlalu, menyisakan trauma, kesedihan, kepedihan, derita, malapetaka, dan juga cinta. Semoga segala duka cepat berlalu. Semoga kita diberi kesabaran dan ketabahan.
Tuesday, May 23, 2006,8:31 AM
 'Daging Akar' Gus tf
'Daging Akar' Gus tfSeperti hampir selalu terjadi, aku dan "pacarsenja"-ku (Kef) tiba paling awal di lokasi acara diskusi buku kumpulan puisi Daging Akar karya Gus tf pada Jumat malan, 19 Mei 2006. Di sana baru ada beberapa butir kepala milik para seleb dunia sastra : Gus tf, Radhar Panca Dahana, Karlina Supeli (pembicara), Hamsad Rangkuti, Zen Hae (moderator), serta pasangan pengantin baru Eka Kurniawan dan Ratih Kumala.
Segera saja Kef dan Gus tf saling berjabat tangan dan mengadu pipi mereka. Kemudian aku diperkenalkan Kef kepada sang penyair Payakumbuh itu. Aku berhasil mendapatkan otografnya di buku Daging Akar (kuperoleh gratis, hasil merayu panitia, menukarnya dengan selembar kartu nama) dan Tambo (novel lama Gus tf).
Karena lapar, aku pesan seporsi spageti dan segelas coklat dingin (minuman favoritku) di meja belakang. Di situ ada dua unit kursi putar bundar seperti yang ada di bar-bar gitu. Kef pesan kentang goreng dan teh panas.
Tak lama kemudian, acara dimulai meski jumlah peserta diskusi cuma 18 orang. Sebagian besar para pelaku sastra sahabat Gust tf seperti yang telah kusebut tadi. Aku tak beranjak dari kursiku sebab selain karena "makan malamku" belum selesai, pun aku nggak pede banget deh duduk bareng sama para penulis itu.
Acara dipandu oleh moderator Zen Hae. Pembicara pertama : Nirwan Arsuka yang, ehem, manis itu. Pembicara kedua : Karlina Supeli. Tadinya aku rada heran juga kenapa Karlina, si 'angkasawati' itu yang diminta jadi pembicara? Tapi aku ingat sih, di buku kumpulan puisi Joko Pinurbo - Kekasihku - ibu yang cantik ini menulis kata pengantarnya. Malam itu, ia lebih banyak menyoroti puisi-puisi Gus tf dari perpektif filsafat.
Sumpah, aku keteteran banget mengikuti perbincangan itu. Bahasanya berat-berat, euy! Apa lagi kemudian ditambah komentar-komentar dari Radhar, Nirwan Dewanto (aku baru tahu ia memakai anting-anting di telinga kirinya hehehe), Binhad Nurohmat, Adi Wicaksono, dan Chavchay (penulis novel Sendalu, kalau tidak salah. Rambutnya lucu banget,kruwil-kruwil seperti punya Rachel Maryam) yang datang kemudian.
Untunglah, aku di belakang tidak sendirian. Di sebelahku duduk manis seorang gadis cantik yang wajahnya mirip Vonny "Bening" itu. Nggak tahunya, ia bernama Farah,seorang artis sinetron. Jujur aja, aku tidak tahu ia main di sinetron apa. Yang jelas, cukup asyik juga ngobrolnya sembari ngemil popcorn manis hidangan dari panitia. Waktu aku tanya padanya puisi-puisi siapa yang ia suka, aku sudah hampir tahu pasti jawabannya adalah Sapardi. Dan benar, memang itulah jawabnya.
Oiya, yang sempat kucatat dari "debat" seru antara dua Nirwan itu adalah : Sia-sia mencari ide dalam puisi-puisi Gus tf. Sama sia-sianya seperti mencari ide pada lukisan abstrak atau musik atonal. Puisi-puisi Gus tf justru mengosongkan diri dari ide, demikian menurut Nirwan Dewanto menanggapi Nirwan Arsuka yang mencoba melihat puisi-puisi Gus tf dari sudut pandang kosmologi. Hanya sedikit yang bisa benar-benar kupahami dari diskusi tersebut.
Duh, malam itu rasanya puisi jadi tampak "seram", kehilangan keindahannya. Hehehe.
Endah Sulwesi
Segera saja Kef dan Gus tf saling berjabat tangan dan mengadu pipi mereka. Kemudian aku diperkenalkan Kef kepada sang penyair Payakumbuh itu. Aku berhasil mendapatkan otografnya di buku Daging Akar (kuperoleh gratis, hasil merayu panitia, menukarnya dengan selembar kartu nama) dan Tambo (novel lama Gus tf).
Karena lapar, aku pesan seporsi spageti dan segelas coklat dingin (minuman favoritku) di meja belakang. Di situ ada dua unit kursi putar bundar seperti yang ada di bar-bar gitu. Kef pesan kentang goreng dan teh panas.
Tak lama kemudian, acara dimulai meski jumlah peserta diskusi cuma 18 orang. Sebagian besar para pelaku sastra sahabat Gust tf seperti yang telah kusebut tadi. Aku tak beranjak dari kursiku sebab selain karena "makan malamku" belum selesai, pun aku nggak pede banget deh duduk bareng sama para penulis itu.
Acara dipandu oleh moderator Zen Hae. Pembicara pertama : Nirwan Arsuka yang, ehem, manis itu. Pembicara kedua : Karlina Supeli. Tadinya aku rada heran juga kenapa Karlina, si 'angkasawati' itu yang diminta jadi pembicara? Tapi aku ingat sih, di buku kumpulan puisi Joko Pinurbo - Kekasihku - ibu yang cantik ini menulis kata pengantarnya. Malam itu, ia lebih banyak menyoroti puisi-puisi Gus tf dari perpektif filsafat.
Sumpah, aku keteteran banget mengikuti perbincangan itu. Bahasanya berat-berat, euy! Apa lagi kemudian ditambah komentar-komentar dari Radhar, Nirwan Dewanto (aku baru tahu ia memakai anting-anting di telinga kirinya hehehe), Binhad Nurohmat, Adi Wicaksono, dan Chavchay (penulis novel Sendalu, kalau tidak salah. Rambutnya lucu banget,kruwil-kruwil seperti punya Rachel Maryam) yang datang kemudian.
Untunglah, aku di belakang tidak sendirian. Di sebelahku duduk manis seorang gadis cantik yang wajahnya mirip Vonny "Bening" itu. Nggak tahunya, ia bernama Farah,seorang artis sinetron. Jujur aja, aku tidak tahu ia main di sinetron apa. Yang jelas, cukup asyik juga ngobrolnya sembari ngemil popcorn manis hidangan dari panitia. Waktu aku tanya padanya puisi-puisi siapa yang ia suka, aku sudah hampir tahu pasti jawabannya adalah Sapardi. Dan benar, memang itulah jawabnya.
Oiya, yang sempat kucatat dari "debat" seru antara dua Nirwan itu adalah : Sia-sia mencari ide dalam puisi-puisi Gus tf. Sama sia-sianya seperti mencari ide pada lukisan abstrak atau musik atonal. Puisi-puisi Gus tf justru mengosongkan diri dari ide, demikian menurut Nirwan Dewanto menanggapi Nirwan Arsuka yang mencoba melihat puisi-puisi Gus tf dari sudut pandang kosmologi. Hanya sedikit yang bisa benar-benar kupahami dari diskusi tersebut.
Duh, malam itu rasanya puisi jadi tampak "seram", kehilangan keindahannya. Hehehe.
Endah Sulwesi
Thursday, May 11, 2006,11:13 PM
 FESTIVAL TOPENG
FESTIVAL TOPENGTak ada yang terasa benar-benar baru dari pementasan Teater Koma malam kemarin (10 Mei 2006) di GBB TIM Jakarta. Lakonnya memang baru, tetapi secara keseluruhan ya "begitu-begitu" saja : sindiran lewat humor-humor segar, dagelan yang kadang-kadang mirip Srimulat, tarian, dan nyanyian dengan iringan musik rancak arahan Idrus Madani. Kali ini bercitarasa tanjidor, musik khas Betawi, dengan gendang dan rebana yang mendonimasi bunyi-bunyian ditingkah seruling dan biola serta alat tiup seperti terompet.
Festival Topeng lakonnya, hasil besutan sutradara Budi Ros sekaligus juga menulis naskahnya ( memenangi Sayembara Penulisan Naskah Drama DKJ 2003). Pementasan sepanjang 2 jam itu merupakan produksi Teater Koma yang ke-110. Rupanya, Nano Riantiarno tengah menjalankan upaya regenerasi di Teater Koma dengan memercayakan penyutradaraan yang selama ini lebih sering dilakukan olehnya kepada "generasi muda" Koma.
Tak bisa dipungkiri, inilah satu-satunya kelompok teater di tanah air yang setiap tahun rutin mengadakan pementasan dan selalu dibanjiri penonton.
Sebenarnya, saya kadang merasa bosan tetapi sekaligus juga rindu menyaksikan aksi mereka yang menghibur : Salim "Julini" Bungsu, Rita Matumona (pementasan kali ini absen), Sari Madjid dengan vokal manjanya yang khas, Idris Pulungan (juga absen), Syaeful Anwar, dan tentu pasangan empu Ratna dan Nano Riantiarno.
Ceritanya tentang Festival Topeng yang berbuntut huru-hara. Festival Topeng merupakan tradisi tahunan masyarakat desa Mosokambang di bawah pimpinan Lurah Jarkoni (diperankan dengan baik oleh Supartono JW. Aktingnya memikat terutama saat adegan merayu Laras). Kali ini, festival rakyat tersebut berbuah keributan, sebab saah satu peserta, Mbah Joyo (N.Riantiarno, muncul dua kali saja : di awal dan akhir) menolak pakai topeng. Ia sudah lelah pakai topeng dan lebih suka memakai wajah aslinya sendiri.
Sikap Mbah Joyo, kontan menyulut amarah panitia penyelenggara festival yang diketuai oleh Mas Genggong (Prijo S.Winardi), mantan lurah. Ujung-ujungnya, Mbah Joyo lenyap tanpa seorang warga desa pun tahu ke mana perginya. Seluruh desa heboh. Mereka kehilangan tokoh panutan. Para pemimpin lepas tangan. Pak Lurah Jarkoni malah asyik masyuk selingkuh dengan Laras yang genit, istri Mas Genggong. Inilah adegan paling mengundang gerrrr penonton.
Raibnya Mbah Joyo melibatkan pula Kasmun, pentolan pemuda desa. Warga desa mencurigai Kasmun (Salim Bungsu) sekongkol dengan Sami'un (Syaeful Anwar) menculik Mbah Joyo. Ketika akhirnya Mbah Joyo pulang, desa pun hidup kembali. Festival topeng diselenggarakan lagi. Pesertanya semakin banyak. Semua orang ingin tampil dengan aneka macam topeng. Semua orang senang pakai topeng.
Bukan Teater Koma namanya bila tampil tanpa muatan kritik dan sindiran kepada para penguasa negeri. Apa lagi di zaman bebas begini. Dahulu saja, dengan dimata-matai intel, mereka tetap berani berkoar melemparkan protes. Meski pun risikonya dilarang mentas.
Demikianlah. Syukur masih ada Teatar Koma yang setia hadir menghampiri, menghibur publik penontonnya; mengajak tertawa, menertawakan keserakahan, ketamakan, dan kemunafikan manusia, kita. Kita yang senang memalsu diri dengan topeng dan kosmetik. Entah sampai kapan.....
endah sulwesi
Festival Topeng lakonnya, hasil besutan sutradara Budi Ros sekaligus juga menulis naskahnya ( memenangi Sayembara Penulisan Naskah Drama DKJ 2003). Pementasan sepanjang 2 jam itu merupakan produksi Teater Koma yang ke-110. Rupanya, Nano Riantiarno tengah menjalankan upaya regenerasi di Teater Koma dengan memercayakan penyutradaraan yang selama ini lebih sering dilakukan olehnya kepada "generasi muda" Koma.
Tak bisa dipungkiri, inilah satu-satunya kelompok teater di tanah air yang setiap tahun rutin mengadakan pementasan dan selalu dibanjiri penonton.
Sebenarnya, saya kadang merasa bosan tetapi sekaligus juga rindu menyaksikan aksi mereka yang menghibur : Salim "Julini" Bungsu, Rita Matumona (pementasan kali ini absen), Sari Madjid dengan vokal manjanya yang khas, Idris Pulungan (juga absen), Syaeful Anwar, dan tentu pasangan empu Ratna dan Nano Riantiarno.
Ceritanya tentang Festival Topeng yang berbuntut huru-hara. Festival Topeng merupakan tradisi tahunan masyarakat desa Mosokambang di bawah pimpinan Lurah Jarkoni (diperankan dengan baik oleh Supartono JW. Aktingnya memikat terutama saat adegan merayu Laras). Kali ini, festival rakyat tersebut berbuah keributan, sebab saah satu peserta, Mbah Joyo (N.Riantiarno, muncul dua kali saja : di awal dan akhir) menolak pakai topeng. Ia sudah lelah pakai topeng dan lebih suka memakai wajah aslinya sendiri.
Sikap Mbah Joyo, kontan menyulut amarah panitia penyelenggara festival yang diketuai oleh Mas Genggong (Prijo S.Winardi), mantan lurah. Ujung-ujungnya, Mbah Joyo lenyap tanpa seorang warga desa pun tahu ke mana perginya. Seluruh desa heboh. Mereka kehilangan tokoh panutan. Para pemimpin lepas tangan. Pak Lurah Jarkoni malah asyik masyuk selingkuh dengan Laras yang genit, istri Mas Genggong. Inilah adegan paling mengundang gerrrr penonton.
Raibnya Mbah Joyo melibatkan pula Kasmun, pentolan pemuda desa. Warga desa mencurigai Kasmun (Salim Bungsu) sekongkol dengan Sami'un (Syaeful Anwar) menculik Mbah Joyo. Ketika akhirnya Mbah Joyo pulang, desa pun hidup kembali. Festival topeng diselenggarakan lagi. Pesertanya semakin banyak. Semua orang ingin tampil dengan aneka macam topeng. Semua orang senang pakai topeng.
Bukan Teater Koma namanya bila tampil tanpa muatan kritik dan sindiran kepada para penguasa negeri. Apa lagi di zaman bebas begini. Dahulu saja, dengan dimata-matai intel, mereka tetap berani berkoar melemparkan protes. Meski pun risikonya dilarang mentas.
Demikianlah. Syukur masih ada Teatar Koma yang setia hadir menghampiri, menghibur publik penontonnya; mengajak tertawa, menertawakan keserakahan, ketamakan, dan kemunafikan manusia, kita. Kita yang senang memalsu diri dengan topeng dan kosmetik. Entah sampai kapan.....
endah sulwesi
Monday, May 08, 2006,7:45 PM
 SELAMAT JALAN, PRAM!
SELAMAT JALAN, PRAM!Minggu pagi, 30 April 2006 jam 11:07:21
Telepon genggam saya bergetar, tanda ada sepucuk sms (short message service) masuk. Ternyata dari Joko Pinurbo, penyair asal Yogyakarta. Isi sms tersebut adalah sebuah puisi sedih menyusul berita meninggalnya Pramoedya Ananta Toer :
SELAMAT JALAN, PRAM.
Selamat jalan, buku.
Selamat sampai di ibukata, ibunya rindu.
Selamat terbang mengarungi ziarah waktu.
Maafkan kami yang belum usai membacamu.
Sejenak saya tertegun. Sajak singkat itu semakin menambah kesedihan saya oleh berita berpulangnya Pramoedya Ananta Toer.
Tidak, saya tidak pernah mengenal Pram secara pribadi. Saya hanya seorang pengagumnya. Pengagum karya-karyanya dan juga semangat perlawanan kepada ketidakadilan yang terus-menerus tanpa lelah disuarakannya. Sejak ia muda belia hingga usia senjanya.
Hidupnya yang delapan puluh satu tahun itu - ia lahir 6 Februari 1925 di Blora - diabdikan sepenuhnya kepada sastra, tanah air, dan kemanusiaan. Kecintaannya pada ibu pertiwi begitu nyata tergambar dalam karya-karyanya. Sikap anti kolonialisme dan imperialisme barat tercermin jelas dalam tulisan-tulisannya, antara lain : Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca), Keluarga Gerilya, Di Tepi Kali Bekasi, dll.
Sekali pernah saya berjumpa langsung dengannya di sebuah acara diskusi buku. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu di Pejaten, Jakarta. Ketika itu pun Pram telah tampak tua dan ringkih. Alat bantu dengar tampak terpasang di telinganya. Rambutnya telah putih seluruhnya. Kaca mata tebal menambah kesan tua wajahnya.
Usai acara saya menghampirinya; menjabat tangannya yang kurus. Ia tersenyum hangat dan tak menolak permintaan saya untuk berfoto dengannya. Peristiwa kecil itu senantiasa saya simpan dalam ingatan; menjadi kenangan yang tak terlupakan. Kami bercakap sebentar. Ia kelihatan agak kewalahan menangkap ucapan saya meski pun saya telah setengah berteriak. Ah..itu tentu karena pendengarannya yang terganggu akibat popor senjata pernah dihantamkan padanya saat penangkapan dirinya di tahun 1965.
Ya, perjalanan hidup suami Maimunah Thamrin ini sebagian dihabiskan di penjara dan sel-sel tahanan. Mulai di masa revolusi oleh pemerintah Belanda (1947-1949) ia dipenjarakan di Bukit Duri, Jakarta, karena menyebarluaskan pamflet antikolonialisme. Demikian juga pada masa pemerintahan Soekarno, ia ditahan karena menulis buku Hoakiau di Indonesia. Kemudian, ketika Orde Baru berkuasa, ia kembali menghuni penjara - lebih tepat kamp kerja paksa - di Pulau Buru selama empat belas tahun (1965-1979) tanpa pernah menjalani proses pengadilan. Ia dicap komunis.
Namun, penjara demi penjara tak mampu memenjarakan jiwanya yang merdeka. Justru dari balik jeruji bui itu Pram melahirkan karya-karya terbaiknya. Tetralogi Buru yang dahsyat itu ditulisnya selama menjalani masa tahanan di Pulau Buru. Sedangkan dari sel Bukit Duri ia menghasilkan Perburuan dan Keluarga Gerilya. Ia tak terbendung.
Barangkali Pramoedya Ananta Toer akan jadi satu-satunya sastrawan Indonesia yang pernah dicalonkan menerima hadiah Nobel. Barangkali, Pram juga satu-satunya sastrawan Indonesia yang karya-karyanya diterjemahkan ke dalam 30 bahasa.
Segala jerih payah, sakit dan getir yang pernah dialaminya tak sia-sia. Berbagai penghargaan bidang sastra ia peroleh dari manca negara. Di antaranya Ramon Magsaysay dari Filipina (1995) dan Freedom to Write Award dari PEN, Amerika Serikat (1998). Sementara dari tanah airnya sendiri apa yang sudah didapatnya? Penjara, pelarangan buku-bukunya, dan pemusnahan naskah karya-karya pentingnya. Ironis.
Dalam buku Saya Terbakar Amarah Sendirian yang memuat wawancara panjangnya dengan Andre Vltchek dan Rossie Indira, memperlihatkan pribadi seorang Pram yang senantiasa gelisah dan resah memikirkan nasib bangsa dan negerinya di ambang kehancuran. Ia meyakini hanya ada satu hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini : revolusi total!
Pada tahun 2000, ia terserang stroke akibat diabetes yang diidapnya. Sejak itu, kondisi fisik dan kesehatannya menurun drastis sehingga tak lagi mampu menulis. "Saya benar-benar tidak bisa menulis lagi. Saya tahu batas kemampuan saya dan saya sudah harus berhenti di sini. Saya ingin berhenti bermimpi." (Saya Terbakar Amarah Sendirian, halaman 124)
Selanjutnya, kegiatan sehari-harinya hanya diisi dengan membakar sampah, mengkliping koran, dan menyiapkan bahan-bahan tulisan untuk ensiklopedi geografi Indonesia yang tengah disusunnya sembari sesekali menerima tamu, baik para sahabatnya yang ingin melepas rindu dan ngobrol-ngobrol mau pun dari kalangan pers untuk keperluan wawancara.
Terakhir sekali, saya meyaksikan tayangan wawancara Pram di sebuah stasiun TV swasta nasional dalam rangka memperingati Hari Kartini. Pram diwawancarai sehubungan karyanya mengenai sejarah Kartini yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Sebuah telaah psikologis kepribadian Kartini melalui surat-suratnya. Novel-novel Pram memang banyak yang berlatar sejarah. Misalnya, Arok-Dedes dan Arus Balik.
Dan kini, ia pun menjadi sejarah. Kembali ke pangkuan ibu pertiwi yang tak habis dicintainya. Nama dan karyanya akan terus hidup seribu tahun lagi. Menjejak di relung-relung hati sanubari mereka yang mengerti arti perjuangan dan kemanusiaan. Selamat jalan, Pram....! Semoga kami bisa mewarisi semangat dan cintamu.
Jakarta, 01 Mei 2006
Endah Sulwesi
Pengagum Pramoedya Ananta Toer
Telepon genggam saya bergetar, tanda ada sepucuk sms (short message service) masuk. Ternyata dari Joko Pinurbo, penyair asal Yogyakarta. Isi sms tersebut adalah sebuah puisi sedih menyusul berita meninggalnya Pramoedya Ananta Toer :
SELAMAT JALAN, PRAM.
Selamat jalan, buku.
Selamat sampai di ibukata, ibunya rindu.
Selamat terbang mengarungi ziarah waktu.
Maafkan kami yang belum usai membacamu.
Sejenak saya tertegun. Sajak singkat itu semakin menambah kesedihan saya oleh berita berpulangnya Pramoedya Ananta Toer.
Tidak, saya tidak pernah mengenal Pram secara pribadi. Saya hanya seorang pengagumnya. Pengagum karya-karyanya dan juga semangat perlawanan kepada ketidakadilan yang terus-menerus tanpa lelah disuarakannya. Sejak ia muda belia hingga usia senjanya.
Hidupnya yang delapan puluh satu tahun itu - ia lahir 6 Februari 1925 di Blora - diabdikan sepenuhnya kepada sastra, tanah air, dan kemanusiaan. Kecintaannya pada ibu pertiwi begitu nyata tergambar dalam karya-karyanya. Sikap anti kolonialisme dan imperialisme barat tercermin jelas dalam tulisan-tulisannya, antara lain : Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca), Keluarga Gerilya, Di Tepi Kali Bekasi, dll.
Sekali pernah saya berjumpa langsung dengannya di sebuah acara diskusi buku. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu di Pejaten, Jakarta. Ketika itu pun Pram telah tampak tua dan ringkih. Alat bantu dengar tampak terpasang di telinganya. Rambutnya telah putih seluruhnya. Kaca mata tebal menambah kesan tua wajahnya.
Usai acara saya menghampirinya; menjabat tangannya yang kurus. Ia tersenyum hangat dan tak menolak permintaan saya untuk berfoto dengannya. Peristiwa kecil itu senantiasa saya simpan dalam ingatan; menjadi kenangan yang tak terlupakan. Kami bercakap sebentar. Ia kelihatan agak kewalahan menangkap ucapan saya meski pun saya telah setengah berteriak. Ah..itu tentu karena pendengarannya yang terganggu akibat popor senjata pernah dihantamkan padanya saat penangkapan dirinya di tahun 1965.
Ya, perjalanan hidup suami Maimunah Thamrin ini sebagian dihabiskan di penjara dan sel-sel tahanan. Mulai di masa revolusi oleh pemerintah Belanda (1947-1949) ia dipenjarakan di Bukit Duri, Jakarta, karena menyebarluaskan pamflet antikolonialisme. Demikian juga pada masa pemerintahan Soekarno, ia ditahan karena menulis buku Hoakiau di Indonesia. Kemudian, ketika Orde Baru berkuasa, ia kembali menghuni penjara - lebih tepat kamp kerja paksa - di Pulau Buru selama empat belas tahun (1965-1979) tanpa pernah menjalani proses pengadilan. Ia dicap komunis.
Namun, penjara demi penjara tak mampu memenjarakan jiwanya yang merdeka. Justru dari balik jeruji bui itu Pram melahirkan karya-karya terbaiknya. Tetralogi Buru yang dahsyat itu ditulisnya selama menjalani masa tahanan di Pulau Buru. Sedangkan dari sel Bukit Duri ia menghasilkan Perburuan dan Keluarga Gerilya. Ia tak terbendung.
Barangkali Pramoedya Ananta Toer akan jadi satu-satunya sastrawan Indonesia yang pernah dicalonkan menerima hadiah Nobel. Barangkali, Pram juga satu-satunya sastrawan Indonesia yang karya-karyanya diterjemahkan ke dalam 30 bahasa.
Segala jerih payah, sakit dan getir yang pernah dialaminya tak sia-sia. Berbagai penghargaan bidang sastra ia peroleh dari manca negara. Di antaranya Ramon Magsaysay dari Filipina (1995) dan Freedom to Write Award dari PEN, Amerika Serikat (1998). Sementara dari tanah airnya sendiri apa yang sudah didapatnya? Penjara, pelarangan buku-bukunya, dan pemusnahan naskah karya-karya pentingnya. Ironis.
Dalam buku Saya Terbakar Amarah Sendirian yang memuat wawancara panjangnya dengan Andre Vltchek dan Rossie Indira, memperlihatkan pribadi seorang Pram yang senantiasa gelisah dan resah memikirkan nasib bangsa dan negerinya di ambang kehancuran. Ia meyakini hanya ada satu hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini : revolusi total!
Pada tahun 2000, ia terserang stroke akibat diabetes yang diidapnya. Sejak itu, kondisi fisik dan kesehatannya menurun drastis sehingga tak lagi mampu menulis. "Saya benar-benar tidak bisa menulis lagi. Saya tahu batas kemampuan saya dan saya sudah harus berhenti di sini. Saya ingin berhenti bermimpi." (Saya Terbakar Amarah Sendirian, halaman 124)
Selanjutnya, kegiatan sehari-harinya hanya diisi dengan membakar sampah, mengkliping koran, dan menyiapkan bahan-bahan tulisan untuk ensiklopedi geografi Indonesia yang tengah disusunnya sembari sesekali menerima tamu, baik para sahabatnya yang ingin melepas rindu dan ngobrol-ngobrol mau pun dari kalangan pers untuk keperluan wawancara.
Terakhir sekali, saya meyaksikan tayangan wawancara Pram di sebuah stasiun TV swasta nasional dalam rangka memperingati Hari Kartini. Pram diwawancarai sehubungan karyanya mengenai sejarah Kartini yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Sebuah telaah psikologis kepribadian Kartini melalui surat-suratnya. Novel-novel Pram memang banyak yang berlatar sejarah. Misalnya, Arok-Dedes dan Arus Balik.
Dan kini, ia pun menjadi sejarah. Kembali ke pangkuan ibu pertiwi yang tak habis dicintainya. Nama dan karyanya akan terus hidup seribu tahun lagi. Menjejak di relung-relung hati sanubari mereka yang mengerti arti perjuangan dan kemanusiaan. Selamat jalan, Pram....! Semoga kami bisa mewarisi semangat dan cintamu.
Jakarta, 01 Mei 2006
Endah Sulwesi
Pengagum Pramoedya Ananta Toer