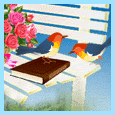AKU DAN SASTRA
Monday, May 08, 2006,7:45 PM
 SELAMAT JALAN, PRAM!
SELAMAT JALAN, PRAM!Minggu pagi, 30 April 2006 jam 11:07:21
Telepon genggam saya bergetar, tanda ada sepucuk sms (short message service) masuk. Ternyata dari Joko Pinurbo, penyair asal Yogyakarta. Isi sms tersebut adalah sebuah puisi sedih menyusul berita meninggalnya Pramoedya Ananta Toer :
SELAMAT JALAN, PRAM.
Selamat jalan, buku.
Selamat sampai di ibukata, ibunya rindu.
Selamat terbang mengarungi ziarah waktu.
Maafkan kami yang belum usai membacamu.
Sejenak saya tertegun. Sajak singkat itu semakin menambah kesedihan saya oleh berita berpulangnya Pramoedya Ananta Toer.
Tidak, saya tidak pernah mengenal Pram secara pribadi. Saya hanya seorang pengagumnya. Pengagum karya-karyanya dan juga semangat perlawanan kepada ketidakadilan yang terus-menerus tanpa lelah disuarakannya. Sejak ia muda belia hingga usia senjanya.
Hidupnya yang delapan puluh satu tahun itu - ia lahir 6 Februari 1925 di Blora - diabdikan sepenuhnya kepada sastra, tanah air, dan kemanusiaan. Kecintaannya pada ibu pertiwi begitu nyata tergambar dalam karya-karyanya. Sikap anti kolonialisme dan imperialisme barat tercermin jelas dalam tulisan-tulisannya, antara lain : Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca), Keluarga Gerilya, Di Tepi Kali Bekasi, dll.
Sekali pernah saya berjumpa langsung dengannya di sebuah acara diskusi buku. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu di Pejaten, Jakarta. Ketika itu pun Pram telah tampak tua dan ringkih. Alat bantu dengar tampak terpasang di telinganya. Rambutnya telah putih seluruhnya. Kaca mata tebal menambah kesan tua wajahnya.
Usai acara saya menghampirinya; menjabat tangannya yang kurus. Ia tersenyum hangat dan tak menolak permintaan saya untuk berfoto dengannya. Peristiwa kecil itu senantiasa saya simpan dalam ingatan; menjadi kenangan yang tak terlupakan. Kami bercakap sebentar. Ia kelihatan agak kewalahan menangkap ucapan saya meski pun saya telah setengah berteriak. Ah..itu tentu karena pendengarannya yang terganggu akibat popor senjata pernah dihantamkan padanya saat penangkapan dirinya di tahun 1965.
Ya, perjalanan hidup suami Maimunah Thamrin ini sebagian dihabiskan di penjara dan sel-sel tahanan. Mulai di masa revolusi oleh pemerintah Belanda (1947-1949) ia dipenjarakan di Bukit Duri, Jakarta, karena menyebarluaskan pamflet antikolonialisme. Demikian juga pada masa pemerintahan Soekarno, ia ditahan karena menulis buku Hoakiau di Indonesia. Kemudian, ketika Orde Baru berkuasa, ia kembali menghuni penjara - lebih tepat kamp kerja paksa - di Pulau Buru selama empat belas tahun (1965-1979) tanpa pernah menjalani proses pengadilan. Ia dicap komunis.
Namun, penjara demi penjara tak mampu memenjarakan jiwanya yang merdeka. Justru dari balik jeruji bui itu Pram melahirkan karya-karya terbaiknya. Tetralogi Buru yang dahsyat itu ditulisnya selama menjalani masa tahanan di Pulau Buru. Sedangkan dari sel Bukit Duri ia menghasilkan Perburuan dan Keluarga Gerilya. Ia tak terbendung.
Barangkali Pramoedya Ananta Toer akan jadi satu-satunya sastrawan Indonesia yang pernah dicalonkan menerima hadiah Nobel. Barangkali, Pram juga satu-satunya sastrawan Indonesia yang karya-karyanya diterjemahkan ke dalam 30 bahasa.
Segala jerih payah, sakit dan getir yang pernah dialaminya tak sia-sia. Berbagai penghargaan bidang sastra ia peroleh dari manca negara. Di antaranya Ramon Magsaysay dari Filipina (1995) dan Freedom to Write Award dari PEN, Amerika Serikat (1998). Sementara dari tanah airnya sendiri apa yang sudah didapatnya? Penjara, pelarangan buku-bukunya, dan pemusnahan naskah karya-karya pentingnya. Ironis.
Dalam buku Saya Terbakar Amarah Sendirian yang memuat wawancara panjangnya dengan Andre Vltchek dan Rossie Indira, memperlihatkan pribadi seorang Pram yang senantiasa gelisah dan resah memikirkan nasib bangsa dan negerinya di ambang kehancuran. Ia meyakini hanya ada satu hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini : revolusi total!
Pada tahun 2000, ia terserang stroke akibat diabetes yang diidapnya. Sejak itu, kondisi fisik dan kesehatannya menurun drastis sehingga tak lagi mampu menulis. "Saya benar-benar tidak bisa menulis lagi. Saya tahu batas kemampuan saya dan saya sudah harus berhenti di sini. Saya ingin berhenti bermimpi." (Saya Terbakar Amarah Sendirian, halaman 124)
Selanjutnya, kegiatan sehari-harinya hanya diisi dengan membakar sampah, mengkliping koran, dan menyiapkan bahan-bahan tulisan untuk ensiklopedi geografi Indonesia yang tengah disusunnya sembari sesekali menerima tamu, baik para sahabatnya yang ingin melepas rindu dan ngobrol-ngobrol mau pun dari kalangan pers untuk keperluan wawancara.
Terakhir sekali, saya meyaksikan tayangan wawancara Pram di sebuah stasiun TV swasta nasional dalam rangka memperingati Hari Kartini. Pram diwawancarai sehubungan karyanya mengenai sejarah Kartini yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Sebuah telaah psikologis kepribadian Kartini melalui surat-suratnya. Novel-novel Pram memang banyak yang berlatar sejarah. Misalnya, Arok-Dedes dan Arus Balik.
Dan kini, ia pun menjadi sejarah. Kembali ke pangkuan ibu pertiwi yang tak habis dicintainya. Nama dan karyanya akan terus hidup seribu tahun lagi. Menjejak di relung-relung hati sanubari mereka yang mengerti arti perjuangan dan kemanusiaan. Selamat jalan, Pram....! Semoga kami bisa mewarisi semangat dan cintamu.
Jakarta, 01 Mei 2006
Endah Sulwesi
Pengagum Pramoedya Ananta Toer
Telepon genggam saya bergetar, tanda ada sepucuk sms (short message service) masuk. Ternyata dari Joko Pinurbo, penyair asal Yogyakarta. Isi sms tersebut adalah sebuah puisi sedih menyusul berita meninggalnya Pramoedya Ananta Toer :
SELAMAT JALAN, PRAM.
Selamat jalan, buku.
Selamat sampai di ibukata, ibunya rindu.
Selamat terbang mengarungi ziarah waktu.
Maafkan kami yang belum usai membacamu.
Sejenak saya tertegun. Sajak singkat itu semakin menambah kesedihan saya oleh berita berpulangnya Pramoedya Ananta Toer.
Tidak, saya tidak pernah mengenal Pram secara pribadi. Saya hanya seorang pengagumnya. Pengagum karya-karyanya dan juga semangat perlawanan kepada ketidakadilan yang terus-menerus tanpa lelah disuarakannya. Sejak ia muda belia hingga usia senjanya.
Hidupnya yang delapan puluh satu tahun itu - ia lahir 6 Februari 1925 di Blora - diabdikan sepenuhnya kepada sastra, tanah air, dan kemanusiaan. Kecintaannya pada ibu pertiwi begitu nyata tergambar dalam karya-karyanya. Sikap anti kolonialisme dan imperialisme barat tercermin jelas dalam tulisan-tulisannya, antara lain : Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca), Keluarga Gerilya, Di Tepi Kali Bekasi, dll.
Sekali pernah saya berjumpa langsung dengannya di sebuah acara diskusi buku. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu di Pejaten, Jakarta. Ketika itu pun Pram telah tampak tua dan ringkih. Alat bantu dengar tampak terpasang di telinganya. Rambutnya telah putih seluruhnya. Kaca mata tebal menambah kesan tua wajahnya.
Usai acara saya menghampirinya; menjabat tangannya yang kurus. Ia tersenyum hangat dan tak menolak permintaan saya untuk berfoto dengannya. Peristiwa kecil itu senantiasa saya simpan dalam ingatan; menjadi kenangan yang tak terlupakan. Kami bercakap sebentar. Ia kelihatan agak kewalahan menangkap ucapan saya meski pun saya telah setengah berteriak. Ah..itu tentu karena pendengarannya yang terganggu akibat popor senjata pernah dihantamkan padanya saat penangkapan dirinya di tahun 1965.
Ya, perjalanan hidup suami Maimunah Thamrin ini sebagian dihabiskan di penjara dan sel-sel tahanan. Mulai di masa revolusi oleh pemerintah Belanda (1947-1949) ia dipenjarakan di Bukit Duri, Jakarta, karena menyebarluaskan pamflet antikolonialisme. Demikian juga pada masa pemerintahan Soekarno, ia ditahan karena menulis buku Hoakiau di Indonesia. Kemudian, ketika Orde Baru berkuasa, ia kembali menghuni penjara - lebih tepat kamp kerja paksa - di Pulau Buru selama empat belas tahun (1965-1979) tanpa pernah menjalani proses pengadilan. Ia dicap komunis.
Namun, penjara demi penjara tak mampu memenjarakan jiwanya yang merdeka. Justru dari balik jeruji bui itu Pram melahirkan karya-karya terbaiknya. Tetralogi Buru yang dahsyat itu ditulisnya selama menjalani masa tahanan di Pulau Buru. Sedangkan dari sel Bukit Duri ia menghasilkan Perburuan dan Keluarga Gerilya. Ia tak terbendung.
Barangkali Pramoedya Ananta Toer akan jadi satu-satunya sastrawan Indonesia yang pernah dicalonkan menerima hadiah Nobel. Barangkali, Pram juga satu-satunya sastrawan Indonesia yang karya-karyanya diterjemahkan ke dalam 30 bahasa.
Segala jerih payah, sakit dan getir yang pernah dialaminya tak sia-sia. Berbagai penghargaan bidang sastra ia peroleh dari manca negara. Di antaranya Ramon Magsaysay dari Filipina (1995) dan Freedom to Write Award dari PEN, Amerika Serikat (1998). Sementara dari tanah airnya sendiri apa yang sudah didapatnya? Penjara, pelarangan buku-bukunya, dan pemusnahan naskah karya-karya pentingnya. Ironis.
Dalam buku Saya Terbakar Amarah Sendirian yang memuat wawancara panjangnya dengan Andre Vltchek dan Rossie Indira, memperlihatkan pribadi seorang Pram yang senantiasa gelisah dan resah memikirkan nasib bangsa dan negerinya di ambang kehancuran. Ia meyakini hanya ada satu hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini : revolusi total!
Pada tahun 2000, ia terserang stroke akibat diabetes yang diidapnya. Sejak itu, kondisi fisik dan kesehatannya menurun drastis sehingga tak lagi mampu menulis. "Saya benar-benar tidak bisa menulis lagi. Saya tahu batas kemampuan saya dan saya sudah harus berhenti di sini. Saya ingin berhenti bermimpi." (Saya Terbakar Amarah Sendirian, halaman 124)
Selanjutnya, kegiatan sehari-harinya hanya diisi dengan membakar sampah, mengkliping koran, dan menyiapkan bahan-bahan tulisan untuk ensiklopedi geografi Indonesia yang tengah disusunnya sembari sesekali menerima tamu, baik para sahabatnya yang ingin melepas rindu dan ngobrol-ngobrol mau pun dari kalangan pers untuk keperluan wawancara.
Terakhir sekali, saya meyaksikan tayangan wawancara Pram di sebuah stasiun TV swasta nasional dalam rangka memperingati Hari Kartini. Pram diwawancarai sehubungan karyanya mengenai sejarah Kartini yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Sebuah telaah psikologis kepribadian Kartini melalui surat-suratnya. Novel-novel Pram memang banyak yang berlatar sejarah. Misalnya, Arok-Dedes dan Arus Balik.
Dan kini, ia pun menjadi sejarah. Kembali ke pangkuan ibu pertiwi yang tak habis dicintainya. Nama dan karyanya akan terus hidup seribu tahun lagi. Menjejak di relung-relung hati sanubari mereka yang mengerti arti perjuangan dan kemanusiaan. Selamat jalan, Pram....! Semoga kami bisa mewarisi semangat dan cintamu.
Jakarta, 01 Mei 2006
Endah Sulwesi
Pengagum Pramoedya Ananta Toer
posted by biru
Permalink ¤
Permalink ¤