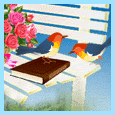AKU DAN SASTRA
Wednesday, January 23, 2008,1:48 PM
 COK SAWITRI : “Pada dasarnya saya anak penurut.”
COK SAWITRI : “Pada dasarnya saya anak penurut.” Para pemenang Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2007 telah diumumkan pekan silam. Salah satu finalisnya adalah Cok Sawitri dengan karyanya Janda dari Jirah. Beberapa hari setelah ‘pesta’ itu usai, Cok masih tinggal di Jakarta untuk menyelesaikan satu dua urusan. Pada Senin (21/1) ia bersedia menerima saya dan seorang wartawati dari sebuah majalah wanita ternama ibukota di tempatnya menginap, rumah besar di bilangan Kayu Putih, Jakarta Timur. Petang itu Cok tampil santai dengan kaus oblong hitam dipadu celana pendek. Rambut panjangnya digelung. Wajahnya polos tanpa riasan make up apa pun.
Para pemenang Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2007 telah diumumkan pekan silam. Salah satu finalisnya adalah Cok Sawitri dengan karyanya Janda dari Jirah. Beberapa hari setelah ‘pesta’ itu usai, Cok masih tinggal di Jakarta untuk menyelesaikan satu dua urusan. Pada Senin (21/1) ia bersedia menerima saya dan seorang wartawati dari sebuah majalah wanita ternama ibukota di tempatnya menginap, rumah besar di bilangan Kayu Putih, Jakarta Timur. Petang itu Cok tampil santai dengan kaus oblong hitam dipadu celana pendek. Rambut panjangnya digelung. Wajahnya polos tanpa riasan make up apa pun.Cok adalah kependekan dari Cokorda, nama yang harus disandangnya sebagai keturunan kasta Brahmana Ksatria. Lahir di Sidemen, Karangasem, Bali pada 1 September 1968 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Sejak masih di TK ia telah senang membaca. Tradisi membaca di keluarga besarnya memungkinkan ia mendapatkan banyak bahan bacaan. Tak heran jika pada usia yang masih sangat belia, SMP kelas 2, puisinya sudah dimuat di Bali Post. “Kelas 3 SD puisiku sudah bagus. Sudah dipuji guru,” tutur Cok mengenang masa awal “percintaannya” dengan puisi. Ia ingat betul, puisi yang dibacakannya di depan kelas itu adalah tentang neneknya.
Tak berhenti pada puisi, Cok mulai mencoba menulis cerpen. Cerpen perdananya yang dimuat di koran lokal, Karya Bakti, berjudul “Kulkul”. Ketika itu ia sudah duduk di bangku SMA di mana ia menjabat pula sebagai ketua OSIS. Ia juga sempat menerbitkan sebuah majalah sekolah bertajuk Tika. Dan sampai sekarang majalah tersebut masih eksis.
“Perjumpaannya” dengan Calon Arang yang lebih suka disebutnya Rangda Ing Jirah, terjadi kira-kira sepuluh tahun lalu. Dimulai tatkala ia yang kuliah di jurusan Administrasi Negara diminta membantu seorang profesor sahabat ayahnya yang tengah melakukan penelitian bidang sosial ekonomi. “Tugas saya menghitung ada berapa sapi di satu desa. Seperti sensus,” cerita Cok sembari mengisap kreteknya dengan nikmat. Lantaran desa yang ditelitinya dekat dengan rumah kakeknya, maka Cok jadi sering singgah setiap usai mengerjakan tugasnya.
Di rumah itu Cok banyak mendapatkan cerita menarik dari seorang tantenya ikhwal sejarah dan silsilah keluarga yang kelak membawanya pada kisah Calon Arang. Untuk lebih memuaskan rasa ingin tahunya, Cok lantas menguliknya dari lontar-lontar milik keluarga. Sayangnya, ia tidak bisa membaca lontar-lontar yang ditulis dalam bahasa Kawi tersebut. Dan tidak sembarang orang boleh membaca atau mendengarkan pembacaannya.
“Tapi saya kan cucu kesayangan. Saya lalu merayu tante saya,” Cok memaparkan lebih lanjut kisahnya. Maka Cok pun diwinten (dibersihkan) melalui sebuah upacara adat untuk akhirnya diizinkan mendengarkan pembacaan lontar-lontar itu. Dan ternyata ia mampu menafsirkan dengan baik naskah-naskah kuno tersebut. Barangkali itu karena, “Pada dasarnya aku anak penurut,” ujar Cok dengan mimik serius, “ kalau aku belajar aku sangat mendengarkan, lho,” lanjutnya lagi seperti ingin meyakinkan.
Namun, baru pada 1992 tercipta puisi “Namaku Dirah” sebagai hasil penelitiannya yang panjang . Empat tahun kemudian puisi tersebut dikembangkan menjadi pementasan teater 4 episode berjudul Pembelaan Dirah.
Novelnya sendiri sesungguhnya tidak pernah ia rencanakan. Itu terjadi pada 4 hari menjelang tahun baru 2006. Dalam 4 hari itu ia menyelesaikan draf novel Calon Arang yang sangat berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Setahun berikutnya, draf tersebut diterbitkan–utuh, tanpa diedit sedikit pun, kecuali untuk urusan salah ketik–sebagai novel liris berjudul Janda dari Jirah.
“Apa hebatnya novel Latin? Karena punya ciri khas. Apa hebatnya Hemingway? Karena dia punya ciri khas. Apa kecirian sastra Indonesia kalau tidak berani bermain di prosa liris?” Cok memberikan alasan sehubungan dengan gaya yang dipilihnya dalam menulis novelnya itu. Dan bagaimana kalau kelak ada yang ingin menerjemahkan Janda dari Jirah ke dalam bahasa Inggris? “Oh, pasti (akan) sakit jiwa translaternya,” sahut Cok.
Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami percakapkan dengan pemilik nama kecil Lilies ini. Tetapi malam yang kian menua memaksa kami menyudahinya.***
posted by biru
Permalink ¤
Permalink ¤