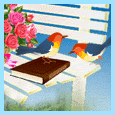AKU DAN SASTRA
Saturday, November 24, 2007,10:53 AM
 Monolog "Sarimin"
Monolog "Sarimin"
POTRET BURAM WAJAH HUKUM KITA
Selama lima malam berturut-turut (14-18 November 2007), Butet Kartaredjasa, berhasil memukau khalayak penonton lewat pertunjukan drama monolog berjudul Sarimin. Atas permintaan banyak penggemarnya, akhirnya panitia Art Summit memenuhi permintaan untuk memperpanjang semalam lagi. Pertunjukan yang digelar di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta ini merupakan salah satu mata acara dari rangkaian besar hajatan Art Summit Indonesia V-2007.
Mengusung naskah garapan Agus Noor, Butet tampil prima di hari pertama show-nya. Masih dengan bumbu dagelan yang khas, putra kelima dari seniman besar Bagong Kussudiardja (alm) ini bukan saja sukses menghibur para hadirin tetapi juga kembali menunjukkan kelasnya sebagai aktor teater dan “Raja Monolog”. Untuk kesekian kalinya berkolaborasi dengan adik kandungnya, Djaduk Ferianto selaku peñata musik, Butet beraksi dengan memboyong spirit teater tradisional ke atas panggung. Terasa sekali bekas-bekas pengaruh Teater Gandrik, kelompok teater asal Yogyakarta yang turut membesarkan ‘karier’ kesenimanan kedua kakak beradik ini. Mengandalkan improvisasi–walaupun tetap mesti patuh pada skenario–pertunjukan monolog tersebut mengalir akrab dan menyatu dengan publik pemirsanya. Mirip lenong Betawi.
Butet yang lahir pada 21 November 1961 dan telanjur lekat dengan predikat tukang banyol itu, kembali melemparkan kritik-kritik sosial lewat lakon tukang topeng monyet ini. Kali ini temanya tentang kebobrokan hukum di negeri bernama Indonesia.
Gagasan awalnya datang dari seorang ahli dan praktisi hukum, Pradjoto, yang terobsesi mengangkat tema hukum ke atas panggung dalam kemasan monolog. Bak gayung bersambut, tawaran itu akhirnya diterima Agus Noor dan Butet, walaupun semula mereka sempat gemetar juga. Segera mereka menyiapkan naskah dan segala sesuatunya. Maka, lantas terciptalah lakon komedi Sarimin, seorang lelaki berusia 54 tahun yang berprofesi sebagai tukang topeng monyet keliling. Semula Agus Noor memberi nama tokohnya Saridin, namun agar lebih ”identik” dengan profesi topeng monyet, diganti Sarimin.
Suatu hari, secara tak sengaja Sarimin menemukan selembar Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lantaran buta huruf, Sarimin tidak tahu siapa pemilik KTP tersebut. Dengan lugu dan berbekal niat baik, Sarimin menyerahkan KTP tersebut ke kantor polisi. Maksudnya agar kelak polisi saja yang mengantarkan ke pemiliknya.
Namun, sial sekali Sarimin. Di kantor polisi itu alih-alih mendapat pujian karena telah berbuat baik, ia malah mendapat masalah. Petugas polisi yang menerimanya justru mempersulit urusan dengan berusaha memeras Sarimin dan mengancam akan mengurungnya di penjara, sebab ternyata KTP itu kepunyaan Hakim Agung. Sarimin dituduh sebagai pencuri karena tidak segera mengembalikannya.
Sarimin yang malang tak bisa membela diri. Akibatnya secara semena-mena ia dijebloskan ke sel tahanan. Pengacara yang ditunjuk untuk membelanya malah sibuk mencari popularitas sendiri. Sarimin hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Sungguh, hukum dan keadilan bukan milik orang kecil seperti dirinya.
Kisah Sarimin ini mencerminkan wajah peradilan dan hukum di negeri kita yang suram dan carut-marut; penuh praktik suap-menyuap, nepotisme, korupsi, dan kolusi. Mulai dari petugas polisi di tingkat bawah hingga para hakim, jaksa, dan pengacara di jajaran atas. Jual beli perkara sudah menjadi rahasia umum yang lumrah. Keadilan untuk semua hanya berhenti pada jargon dan slogan kosong belaka.
Tokoh Sarimin merupakan perwakilan ‘orang kecil’ yang jujur kendati tak pernah mengecap bangku sekolah dan buta hukum sama sekali. Kejujuran sudah tak laku lagi dijual di sini. Segalanya mesti pakai uang, uang, dan uang. Jika punya masalah dengan hukum, lebih baik selesaikan secara kekeluargaan, sebab jika dibawa ke polisi atau meja hijau, urusannya akan bertambah panjang dan rumit. Mengadu kehilangan ayam, bisa-bisa kita malah jadi kehilangan kambing.
Monolog yang berdurasi sekitar 100 menit ini, dari awal hingga akhir mampu membuat penonton ger-geran. Butet seolah-olah tengah mendongengi penonton. Beberapa kali ia bahkan melibatkan penonton dalam dialognya. Butet juga melakukan sendiri perubahan setting panggung, menggeser-geser dan memindah-mindahkan properti. Sesekali Djaduk dan awak musik lainnya ikut nyeletuk. Sekali lagi, mengingatkan kita pada gaya Teater Gandrik.
Suksesnya pertunjukan monodrama ini tak lepas dari sebuah kerja sama tim yang solid. Mereka antara lain : Ong Harry Wahyu (Penata Artistik), Zuki atau yang lebih dikenal dengan nama Kill The DJ (Pengontrol Dramatik), Felix Antonius Widyatmoko (Penata Suara), Rulyani Isfihana (Penata Busana), dll.
Berikutnya, monolog ini akan digelar juga di Yogyakarta pada 26 dan 27 November 2007. Mestinya, dalam setiap pergelaran, diundang pula para pejabat polisi dan pengadilan setempat. Siapa tahu kritik-kritik yang dilontarkan bisa lebih efektif karena langsung sampai ke sasarannya. ***
(Endah Sulwesi)
Selama lima malam berturut-turut (14-18 November 2007), Butet Kartaredjasa, berhasil memukau khalayak penonton lewat pertunjukan drama monolog berjudul Sarimin. Atas permintaan banyak penggemarnya, akhirnya panitia Art Summit memenuhi permintaan untuk memperpanjang semalam lagi. Pertunjukan yang digelar di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta ini merupakan salah satu mata acara dari rangkaian besar hajatan Art Summit Indonesia V-2007.
Mengusung naskah garapan Agus Noor, Butet tampil prima di hari pertama show-nya. Masih dengan bumbu dagelan yang khas, putra kelima dari seniman besar Bagong Kussudiardja (alm) ini bukan saja sukses menghibur para hadirin tetapi juga kembali menunjukkan kelasnya sebagai aktor teater dan “Raja Monolog”. Untuk kesekian kalinya berkolaborasi dengan adik kandungnya, Djaduk Ferianto selaku peñata musik, Butet beraksi dengan memboyong spirit teater tradisional ke atas panggung. Terasa sekali bekas-bekas pengaruh Teater Gandrik, kelompok teater asal Yogyakarta yang turut membesarkan ‘karier’ kesenimanan kedua kakak beradik ini. Mengandalkan improvisasi–walaupun tetap mesti patuh pada skenario–pertunjukan monolog tersebut mengalir akrab dan menyatu dengan publik pemirsanya. Mirip lenong Betawi.
Butet yang lahir pada 21 November 1961 dan telanjur lekat dengan predikat tukang banyol itu, kembali melemparkan kritik-kritik sosial lewat lakon tukang topeng monyet ini. Kali ini temanya tentang kebobrokan hukum di negeri bernama Indonesia.
Gagasan awalnya datang dari seorang ahli dan praktisi hukum, Pradjoto, yang terobsesi mengangkat tema hukum ke atas panggung dalam kemasan monolog. Bak gayung bersambut, tawaran itu akhirnya diterima Agus Noor dan Butet, walaupun semula mereka sempat gemetar juga. Segera mereka menyiapkan naskah dan segala sesuatunya. Maka, lantas terciptalah lakon komedi Sarimin, seorang lelaki berusia 54 tahun yang berprofesi sebagai tukang topeng monyet keliling. Semula Agus Noor memberi nama tokohnya Saridin, namun agar lebih ”identik” dengan profesi topeng monyet, diganti Sarimin.
Suatu hari, secara tak sengaja Sarimin menemukan selembar Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lantaran buta huruf, Sarimin tidak tahu siapa pemilik KTP tersebut. Dengan lugu dan berbekal niat baik, Sarimin menyerahkan KTP tersebut ke kantor polisi. Maksudnya agar kelak polisi saja yang mengantarkan ke pemiliknya.
Namun, sial sekali Sarimin. Di kantor polisi itu alih-alih mendapat pujian karena telah berbuat baik, ia malah mendapat masalah. Petugas polisi yang menerimanya justru mempersulit urusan dengan berusaha memeras Sarimin dan mengancam akan mengurungnya di penjara, sebab ternyata KTP itu kepunyaan Hakim Agung. Sarimin dituduh sebagai pencuri karena tidak segera mengembalikannya.
Sarimin yang malang tak bisa membela diri. Akibatnya secara semena-mena ia dijebloskan ke sel tahanan. Pengacara yang ditunjuk untuk membelanya malah sibuk mencari popularitas sendiri. Sarimin hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Sungguh, hukum dan keadilan bukan milik orang kecil seperti dirinya.
Kisah Sarimin ini mencerminkan wajah peradilan dan hukum di negeri kita yang suram dan carut-marut; penuh praktik suap-menyuap, nepotisme, korupsi, dan kolusi. Mulai dari petugas polisi di tingkat bawah hingga para hakim, jaksa, dan pengacara di jajaran atas. Jual beli perkara sudah menjadi rahasia umum yang lumrah. Keadilan untuk semua hanya berhenti pada jargon dan slogan kosong belaka.
Tokoh Sarimin merupakan perwakilan ‘orang kecil’ yang jujur kendati tak pernah mengecap bangku sekolah dan buta hukum sama sekali. Kejujuran sudah tak laku lagi dijual di sini. Segalanya mesti pakai uang, uang, dan uang. Jika punya masalah dengan hukum, lebih baik selesaikan secara kekeluargaan, sebab jika dibawa ke polisi atau meja hijau, urusannya akan bertambah panjang dan rumit. Mengadu kehilangan ayam, bisa-bisa kita malah jadi kehilangan kambing.
Monolog yang berdurasi sekitar 100 menit ini, dari awal hingga akhir mampu membuat penonton ger-geran. Butet seolah-olah tengah mendongengi penonton. Beberapa kali ia bahkan melibatkan penonton dalam dialognya. Butet juga melakukan sendiri perubahan setting panggung, menggeser-geser dan memindah-mindahkan properti. Sesekali Djaduk dan awak musik lainnya ikut nyeletuk. Sekali lagi, mengingatkan kita pada gaya Teater Gandrik.
Suksesnya pertunjukan monodrama ini tak lepas dari sebuah kerja sama tim yang solid. Mereka antara lain : Ong Harry Wahyu (Penata Artistik), Zuki atau yang lebih dikenal dengan nama Kill The DJ (Pengontrol Dramatik), Felix Antonius Widyatmoko (Penata Suara), Rulyani Isfihana (Penata Busana), dll.
Berikutnya, monolog ini akan digelar juga di Yogyakarta pada 26 dan 27 November 2007. Mestinya, dalam setiap pergelaran, diundang pula para pejabat polisi dan pengadilan setempat. Siapa tahu kritik-kritik yang dilontarkan bisa lebih efektif karena langsung sampai ke sasarannya. ***
(Endah Sulwesi)
posted by biru
Permalink ¤
Permalink ¤