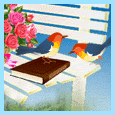AKU DAN SASTRA
Sunday, December 17, 2006,1:00 PM
 Wawancara dengan Sulaiman Tripa : Mengenang 2 Tahun Tsunami
Wawancara dengan Sulaiman Tripa : Mengenang 2 Tahun TsunamiDua puluh enam Desember dua tahun yang lalu, bencana besar melanda ujung utara Pulau Sumatra, khususnya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .Dua tahun yang lalu, tiba-tiba saja kosa-kata tsunami menjadi akrab sekaligus momok bagi kita. Beribu jiwa hilang bersama raga yang tertimbun reruntuhan atau dihanyutkan gelombang maha dahsyat. Dalam sekejap, Aceh dan sekitarnya luluh lantak tak berdaya, rata dengan tanah. Seluruh negeri turut terluka rasanya.
Dan kini, setelah dua tahun berlalu, Serambi Mekah itu tengah berbenah, menyembuhkan luka dan trauma, menumbuhkan kembali asa yang sempat meredup.
Berikut ini bincang-bincang kami bersama Sulaiman Tripa, penulis novel asal Banda Aceh dalam rangka mengenang kembali tragedi tsunami. Ia kami temui seusai acara Lampion Sastra IV di Taman Ismali Marzuki beberapa waktu lalu. Acara tersebut mengambil tema “Sastra Bencana”. Sulaiman Tripa diundang untuk membacakan salah satu cerpennya yang berjudul "Gegasi Di Sebalik Bukit". Novel terakhir yang ditulisnya adalah Malam Memeluk Intan (2005).
Pekan depan tepat dua tahun tragedi tsunami. Bagaimana geliat sastra di NAD pasca bencana besar itu? Ada perbedaan signifikan dengan sebelum bencana?
Saya kira luar biasa geliatnya. Sehabis tsunami, puluhan buku sastra terbit yang ditulis oleh sastrawan di Aceh. Ini yang sungguh jarang terlihat sebelum tsunami. Sebelum tsunami, sastrawan yang meluncurkan satu buku, sudah luar biasa. Tapi pascatsunami, sastrawan sudah meluncurkan puluhan buku, dan itu dilakukan tak hanya di Aceh. Itu dilakukan di Padang, Jakarta, Jogjakarta, Bandung. Ini perkembangan luar biasa menurut saya.
Buku jadi salah satu alat ukur, salah satu. Kemudian ada yang lain, beberapa sastrawan Aceh kerap terlihat karya mereka di berbagai media besar. Setelah tsunami juga, beberapa sastrawan Aceh terlihat begitu fenomenal. Ini saya kira beberapa hal yang menampakkan geliat itu semakin besar, artinya, banyak sastrawan yang sebelumnya seperti tidak ada momentum, sehingga karya mereka tak dikenal, padahal mereka tak kalah dalam bersaing dalam hal kualitas. Namun demikian, kondisi ini diakui belum dominan.
Menurut Anda bagaimana mestinya sastra/seni mengambil peran/memosisikan diri dalam setiap peristiwa, termasuk bencana?
Saya cenderung melihat 'wilayah kerja', wilayah peran. Maksudnya, apa yang bisa dilakukan oleh seniman, ya harus dilakukan. Begitu juga dengan elemen masyarakat yang lain. Jadi, alat ukur di sini, ya peran-peran berkesenian. Ini sudah dilakukan di Aceh di awal-awal tsunami oleh teman-teman yang juga mengalami korban anggota keluarganya dan harta-benda, tapi masih berkesenian untuk memberikan (minimal) semangat. Saya kira, tapi saya tak tahu persis, bahwa hal ini juga dilakukan oleh teman-teman di Yogyakarta.
Ini bagian dari posisi itu. Bahwa seniman merespons bencana dengan karya yang bersedih, itu satu persoalan, tapi saya kira dengan kesedihan itu harus bisa membangkitkan semangat. Ini juga harus diperhatikan. Maksudnya, kita bersedih ya, tapi apakah tidak bisa dengan karya yang 'sedih' tapi meneguhkan semangat melanjutkan hidup. Di manapun terjadinya bencana, hal ini menurut saya, harus diperhatikan.
Bagaimana sikap pemerintah daerah yang sekarang terhadap perkembangan dunia seni dan sastra di NAD dibandingkan dahulu sebelum reformasi?
Saya harus bilang bahwa tidak begitu menggembirakan. Tapi dalam beberapa hal sudah menampakkan kemajuan, ihwal misalnya ada seniman yang memperoleh penghargaan. Tapi secara umum, masih sangat terbatas.
Saya adalah salah seorang yang mengukur komitmen pemerintah itu tidak hanya dengan dana. Dana salah satu kebutuhan, bukan satu-satunya. Tapi bagaimana tentang perlindungan terhadap karya seniman, saya kira ini masih bisa dipertanyakan --walau dalam konteks Aceh, memang ada hal yang juga harus dilihat, yakni pelaksanaan syariat Islam yang juga dikritisi secara terus-menerus agar tercapai sasaran yang diinginkan.
Hal-hal seperti ini, termasuk bagaimana pemerintah memberikan semangat agar seniman tetap berkarya menjadi penting. Jangan sampai ekspresi seni dalam acara-acara penting justru ditempatkan di waktu habis acara, sama kayak orang mau makan. Jadi ke depan, porsi kesenian saya kira jangan sampai lagi seperti itu. Karena saya yakin, nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah seni terkandung muatan untuk kelembutan peradaban.
Apa dampak terbesar bagi masyarakat Aceh dengan banyaknya pihak (pemerintah maupun non pemerintah) yang masuk dalam rangka memulihkan Aceh kembali?
Yang dimaksudkan mungkin dampak negatif ya! Saya kira ada. Yang sangat kurang diberdayakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi adalah keikutsertaan masyarakat korban di dalamnya. Yang saya lihat sekarang adalah, masyarakat korban tergantung. Masyarakat seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dengan kondisi seperti sekarang, masyarakat korban juga masih banyak masalah, belum semua kebutuhan mereka terpenuhi. Tapi yang jelas, menurut saya ini dampak negatif. Belum lagi misalnya, pascatsunami sudah lahir satu golongan baru yang 'mewah' sebagai pekerja berbagai program. Ketika golongan ini --tepatnya sebagian pekerja di Aceh yang bermewah-mewah, akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi Aceh. Bagi masyarakat sendiri, saya yakin mereka tahu tentang apa yang terlihat. Saya kira ini tak bisa disembunyikan. Mereka yang menjadi korban, tahu banyak pekerja di Aceh yang memiliki pendapatan besar, tapi masalah mereka belum terselesaikan secara tuntas. Ini akan bermasalah di kemudian hari.
Satu hal lagi yang cenderung banyak orang melihat secara sederhana adalah bagaimana setelah proses ini selesai. Katakanlah 2009. Tahun 2007 saja, banyak program yang sudah selesai, ini akan berdampak kurang baik. Banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Di samping itu, orang-orang yang sudah terbiasa dengan pendapatan tinggi, lalu menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan, lantas ketika semua berhenti, menurut saya ini akan menjadi masalah besar.
Apa akan ada acara khusus memperingati dua tahun tsunami, khususnya yang diselenggarakan oleh para sastrawan dan seniman Aceh?
Belum tahu. Tapi kami di Lapena, merencanakan ada satu kegiatan yang bisa mengingatkan semua pihak melalui karya sastra untuk selalu melakukan evaluasi dan introspeksi. Mungkin namanya "Dua Tahun Tsunami dan Sastra di Aceh".
Kami sedang berusaha mengajak kerjasama dengan kampus. Ini agar berbagai konsep, gagasan, dari sastra, juga bermuatan akademis. Kami merasa itu sangat penting, agar orang juga berfikir bahwa sastra juga berpengaruh dalam pembangunan sebuah peradaban.
Nah, dua tahun ini, kami sebenarnya ingin menghadirkan lagi momentum, untuk melihat apa-apa yang perlu dievaluasi, dan mengingatkan melalui sastra, bahwa masyarakat korban yan merupakan orang yang menjadi 'sebab' hingga semua bantuan hadir ke Aceh.
Apa rencana dan target di tahun mendatang sehubungan dengan karier menulis Anda?
Saya sangat kepingin menyelesaikan sebuah novel serius. Saat ini belum, saya masih terus menulis, walau tak terfokus. Moto saya kan "Menulislah biar orang-orang membacanya". Maka saya tak pernah memilah saya harus menulis sastra atau nonsastra. Tapi yang jelas, harus bermanfaat bagi umat manusia. Makanya jangan heran, banyak juga tulisan saya yang di luar sastra, walau bahasanya mungkin sedikit sastra.
Saat ini saya sudah mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Saya juga berusaha menjadikan bahasa sastra sebagai penunjang, karena memang sangat membantu yang saya rasakan. Banyak masalah, ketika dirasionalisasikan, ternyata sangat enak menggunakan bahasa sastra. Saya sudah merasakan manfaatnya itu. Dan, saya kira, ini juga akan sangat membantu dalam bidang-bidang yang lain.
Yang jelas, saya tak ingin berhenti menulis. Dengan menulis, juga akan mengurangi pergulatan masalah dalam diri saya sendiri. Akhirnya, menulis merupakan salah satu pintu untuk menyelesaikan konflik dalam diri. Menulis, juga sebuah manajemen pengelolaan emosi pada akhirnya.
Endah Sulwesi
wawancara ini dimuat di tabloid PARLE edisi 66, 17 Desember 2006.
Dan kini, setelah dua tahun berlalu, Serambi Mekah itu tengah berbenah, menyembuhkan luka dan trauma, menumbuhkan kembali asa yang sempat meredup.
Berikut ini bincang-bincang kami bersama Sulaiman Tripa, penulis novel asal Banda Aceh dalam rangka mengenang kembali tragedi tsunami. Ia kami temui seusai acara Lampion Sastra IV di Taman Ismali Marzuki beberapa waktu lalu. Acara tersebut mengambil tema “Sastra Bencana”. Sulaiman Tripa diundang untuk membacakan salah satu cerpennya yang berjudul "Gegasi Di Sebalik Bukit". Novel terakhir yang ditulisnya adalah Malam Memeluk Intan (2005).
Pekan depan tepat dua tahun tragedi tsunami. Bagaimana geliat sastra di NAD pasca bencana besar itu? Ada perbedaan signifikan dengan sebelum bencana?
Saya kira luar biasa geliatnya. Sehabis tsunami, puluhan buku sastra terbit yang ditulis oleh sastrawan di Aceh. Ini yang sungguh jarang terlihat sebelum tsunami. Sebelum tsunami, sastrawan yang meluncurkan satu buku, sudah luar biasa. Tapi pascatsunami, sastrawan sudah meluncurkan puluhan buku, dan itu dilakukan tak hanya di Aceh. Itu dilakukan di Padang, Jakarta, Jogjakarta, Bandung. Ini perkembangan luar biasa menurut saya.
Buku jadi salah satu alat ukur, salah satu. Kemudian ada yang lain, beberapa sastrawan Aceh kerap terlihat karya mereka di berbagai media besar. Setelah tsunami juga, beberapa sastrawan Aceh terlihat begitu fenomenal. Ini saya kira beberapa hal yang menampakkan geliat itu semakin besar, artinya, banyak sastrawan yang sebelumnya seperti tidak ada momentum, sehingga karya mereka tak dikenal, padahal mereka tak kalah dalam bersaing dalam hal kualitas. Namun demikian, kondisi ini diakui belum dominan.
Menurut Anda bagaimana mestinya sastra/seni mengambil peran/memosisikan diri dalam setiap peristiwa, termasuk bencana?
Saya cenderung melihat 'wilayah kerja', wilayah peran. Maksudnya, apa yang bisa dilakukan oleh seniman, ya harus dilakukan. Begitu juga dengan elemen masyarakat yang lain. Jadi, alat ukur di sini, ya peran-peran berkesenian. Ini sudah dilakukan di Aceh di awal-awal tsunami oleh teman-teman yang juga mengalami korban anggota keluarganya dan harta-benda, tapi masih berkesenian untuk memberikan (minimal) semangat. Saya kira, tapi saya tak tahu persis, bahwa hal ini juga dilakukan oleh teman-teman di Yogyakarta.
Ini bagian dari posisi itu. Bahwa seniman merespons bencana dengan karya yang bersedih, itu satu persoalan, tapi saya kira dengan kesedihan itu harus bisa membangkitkan semangat. Ini juga harus diperhatikan. Maksudnya, kita bersedih ya, tapi apakah tidak bisa dengan karya yang 'sedih' tapi meneguhkan semangat melanjutkan hidup. Di manapun terjadinya bencana, hal ini menurut saya, harus diperhatikan.
Bagaimana sikap pemerintah daerah yang sekarang terhadap perkembangan dunia seni dan sastra di NAD dibandingkan dahulu sebelum reformasi?
Saya harus bilang bahwa tidak begitu menggembirakan. Tapi dalam beberapa hal sudah menampakkan kemajuan, ihwal misalnya ada seniman yang memperoleh penghargaan. Tapi secara umum, masih sangat terbatas.
Saya adalah salah seorang yang mengukur komitmen pemerintah itu tidak hanya dengan dana. Dana salah satu kebutuhan, bukan satu-satunya. Tapi bagaimana tentang perlindungan terhadap karya seniman, saya kira ini masih bisa dipertanyakan --walau dalam konteks Aceh, memang ada hal yang juga harus dilihat, yakni pelaksanaan syariat Islam yang juga dikritisi secara terus-menerus agar tercapai sasaran yang diinginkan.
Hal-hal seperti ini, termasuk bagaimana pemerintah memberikan semangat agar seniman tetap berkarya menjadi penting. Jangan sampai ekspresi seni dalam acara-acara penting justru ditempatkan di waktu habis acara, sama kayak orang mau makan. Jadi ke depan, porsi kesenian saya kira jangan sampai lagi seperti itu. Karena saya yakin, nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah seni terkandung muatan untuk kelembutan peradaban.
Apa dampak terbesar bagi masyarakat Aceh dengan banyaknya pihak (pemerintah maupun non pemerintah) yang masuk dalam rangka memulihkan Aceh kembali?
Yang dimaksudkan mungkin dampak negatif ya! Saya kira ada. Yang sangat kurang diberdayakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi adalah keikutsertaan masyarakat korban di dalamnya. Yang saya lihat sekarang adalah, masyarakat korban tergantung. Masyarakat seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dengan kondisi seperti sekarang, masyarakat korban juga masih banyak masalah, belum semua kebutuhan mereka terpenuhi. Tapi yang jelas, menurut saya ini dampak negatif. Belum lagi misalnya, pascatsunami sudah lahir satu golongan baru yang 'mewah' sebagai pekerja berbagai program. Ketika golongan ini --tepatnya sebagian pekerja di Aceh yang bermewah-mewah, akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi Aceh. Bagi masyarakat sendiri, saya yakin mereka tahu tentang apa yang terlihat. Saya kira ini tak bisa disembunyikan. Mereka yang menjadi korban, tahu banyak pekerja di Aceh yang memiliki pendapatan besar, tapi masalah mereka belum terselesaikan secara tuntas. Ini akan bermasalah di kemudian hari.
Satu hal lagi yang cenderung banyak orang melihat secara sederhana adalah bagaimana setelah proses ini selesai. Katakanlah 2009. Tahun 2007 saja, banyak program yang sudah selesai, ini akan berdampak kurang baik. Banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Di samping itu, orang-orang yang sudah terbiasa dengan pendapatan tinggi, lalu menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan, lantas ketika semua berhenti, menurut saya ini akan menjadi masalah besar.
Apa akan ada acara khusus memperingati dua tahun tsunami, khususnya yang diselenggarakan oleh para sastrawan dan seniman Aceh?
Belum tahu. Tapi kami di Lapena, merencanakan ada satu kegiatan yang bisa mengingatkan semua pihak melalui karya sastra untuk selalu melakukan evaluasi dan introspeksi. Mungkin namanya "Dua Tahun Tsunami dan Sastra di Aceh".
Kami sedang berusaha mengajak kerjasama dengan kampus. Ini agar berbagai konsep, gagasan, dari sastra, juga bermuatan akademis. Kami merasa itu sangat penting, agar orang juga berfikir bahwa sastra juga berpengaruh dalam pembangunan sebuah peradaban.
Nah, dua tahun ini, kami sebenarnya ingin menghadirkan lagi momentum, untuk melihat apa-apa yang perlu dievaluasi, dan mengingatkan melalui sastra, bahwa masyarakat korban yan merupakan orang yang menjadi 'sebab' hingga semua bantuan hadir ke Aceh.
Apa rencana dan target di tahun mendatang sehubungan dengan karier menulis Anda?
Saya sangat kepingin menyelesaikan sebuah novel serius. Saat ini belum, saya masih terus menulis, walau tak terfokus. Moto saya kan "Menulislah biar orang-orang membacanya". Maka saya tak pernah memilah saya harus menulis sastra atau nonsastra. Tapi yang jelas, harus bermanfaat bagi umat manusia. Makanya jangan heran, banyak juga tulisan saya yang di luar sastra, walau bahasanya mungkin sedikit sastra.
Saat ini saya sudah mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Saya juga berusaha menjadikan bahasa sastra sebagai penunjang, karena memang sangat membantu yang saya rasakan. Banyak masalah, ketika dirasionalisasikan, ternyata sangat enak menggunakan bahasa sastra. Saya sudah merasakan manfaatnya itu. Dan, saya kira, ini juga akan sangat membantu dalam bidang-bidang yang lain.
Yang jelas, saya tak ingin berhenti menulis. Dengan menulis, juga akan mengurangi pergulatan masalah dalam diri saya sendiri. Akhirnya, menulis merupakan salah satu pintu untuk menyelesaikan konflik dalam diri. Menulis, juga sebuah manajemen pengelolaan emosi pada akhirnya.
Endah Sulwesi
wawancara ini dimuat di tabloid PARLE edisi 66, 17 Desember 2006.
posted by biru
Permalink ¤
Permalink ¤