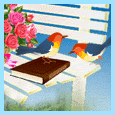AKU DAN SASTRA
Thursday, November 29, 2007,1:36 PM
 Urip Herdiman Kambali
Urip Herdiman Kambali
IA YANG JATUH CINTA PADA KARNA
Nama Urip Herdiman Kambali relatif masih baru di jagat sastra Nusantara. Namanya praktis baru mulai sering dibincang sejak buku kumpulan puisinya, Meditasi Sepanjang Zaman di Borobudur, berhasil menjadi salah satu finalis Khatulistiwa Literary Award (KLA) tahun lalu. Melalui buku yang dicetak dengan biaya sendiri itu, Urip melenggang mantap, terjun ke arena puisi.
“Tetapi sebetulnya saya sudah menulis puisi sejak SMA”, katanya memulai kisah. Itu berarti antara tahun 1981-1984. Tak sekadar menulis, ia pun pernah pula mengikuti lomba baca puisi serta aktif di beberapa komunitas sastra, seperti Gorong-Gorong Budaya dan Apresiasi Sastra. Putra kedua pasangan Kresno Kambali dan Soebijarsinih Soehoed–keduanya telah almarhum–ini mengaku tertarik pula pada filsafat dan wayang. Rumitnya filsafat sempat membawa Urip singgah sejenak menekuni ibu segala ilmu tersebut di STF Driyarkara meski tak selesai (1992-1993). Dua tahun sebelumnya, penggemar berat sajak-sajak Goenawan Mohamad dan Joko Pinurbo ini, menamatkan kuliahnya di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1990).
Adapun wayang adalah yang memunculkan gagasan di kepala lelaki berusia 42 tahun ini untuk menerbitkan antologi puisinya yang kedua. Buku yang diluncurkan pada 9 November 2007 lalu diberi judul Karna, Ksatria di Jalan Panah. Acara launching-nya berlangsung di Café Omah Sendok, Jakarta Selatan. Dihadiri segenap sahabat dan kerabat Urip dari berbagai kalangan, termasuk pendukung utamanya: teman-teman di Perkumpulan Meditasi Bali Usada.
Telah lama pegawai media internal di sebuah BUMN ini menggeluti meditasi ala buddhis. Di perkumpulan ini pula Urip memperoleh bantuan dana bagi penerbitan buku puisinya tersebut yang memakan biaya lebih dari sepuluh juta rupiah.
“Meskipun saya pernah masuk lima besar KLA 2006, tetapi ternyata bukan jaminan bisa dengan mudah menembus para penerbit”, ujar Urip dengan wajah prihatin.
Demikianlah adanya kenyataan di negeri ini. Puisi belum mendapat tempat yang “layak” di ranah sastra kita. Layak di sini bermakna tidak banyak penggemar (pembaca), tidak seperti prosa. Sehingga para penerbit mesti berhitung dengan sangat cermat sebelum memutuskan untuk menerbitkan sebuah buku puisi. Lantaran itulah Urip lantas memilih menerbitkan sendiri karyanya secara swadaya dan swadana.
Menyangkut perkara ide sebuah puisi, Urip bisa memulungnya dari mana saja. Namun, khusus untuk buku-buku yang telah dan kelak akan diterbitkannya, ia menciptakan sajak-sajak tematis yang dipikirkan dan direncanakan masak-masak. Antologi tematis seperti Karna ini merupakan salah satu obsesinya dalam berpuisi.
Dan tentang Karna, Urip mendapatkan ilhamnya pertama kali usai membaca Mahabharata hasil gubahan Purwadi sekitar dua tahun silam. Saat itu, pria kurus kelahiran 15 Juli 1965 ini baru ngeh dan merasa jatuh cinta pada karakter si “Anak Haram”, Karna yang gugur secara ksatria di tangan Arjuna di medan perang Bharata Yudha.
Sesungguhnya, pewayangan bukanlah barang baru dan asing bagi Urip. Sejak kecil ia telah dikenalkan oleh sang ayah kepada kesenian ini. Pun ia juga melahap dengan rakusnya kisah-kisah wayang tersebut lewat majalah Si Kuncung yang terbit pada 1970-an serta versi komik Mahabharata karya R.A.Kosasih yang legendaris itu. Belakangan, bacaannya tentang wayang (Mahabharata dan Ramayana) meluas hingga ke banyak versi. Misalnya, versi India karya P.Lal terbitan Balai Pustaka. Dari kitab-kitab yang dibacanya itu, urip menemukan beberapa perbedaan yang mencolok dan bertolak belakang, khususnya pada tokoh Karna.
Dalam versi India, dituturkan bahwa tidak banyak yang tahu Karna itu sebenarnya adalah saudara seibu dengan Pandawa Lima. Ibu mereka, Kunti, sebelum kawin dengan Pandu Dewanata, telah lebih dulu melahirkan Karna dari hasil hubungan cinta dengan Batara Surya. Sementara menurut lakon wayang Jawa, para Pandawa dan Karna telah mengetahui bahwa mereka adalah kakak beradik.
Setelah melalui perenungan yang dalam, Urip memutuskan untuk setia pada alur kisah dari negeri Mahatma Gandhi. Pertimbangannya semata-mata demi dramatika cerita dan mendapatkan efek puitik untuk sajak-sajaknya. Maka, lahirlah 23 puisi bertopik Karna, sejak kelahiran hingga ajalnya. Semua terangkum dalam buku yang sudah disebut di atas tadi.
Nah, sebagaimana yang dicita-citakannya, kini Urip telah mulai merancang buku antologi puisi selanjutnya. Kepinginnya sih bisa terbit secara berkala setiap dua tahun. Di benaknya telah ada konsep tema “mimpi dalam mimpi” yang menunggu direalisasikan. Akankah Urip sanggup terus tegar berkecimpung bersama puisi-puisi yang telah menjadi “jalan hidup”-nya, kendati, seperti kata Wayan Sunarta, nasib puisi (di negeri ini masih) seperti kisah Karna? Semoga saja….***
Nama Urip Herdiman Kambali relatif masih baru di jagat sastra Nusantara. Namanya praktis baru mulai sering dibincang sejak buku kumpulan puisinya, Meditasi Sepanjang Zaman di Borobudur, berhasil menjadi salah satu finalis Khatulistiwa Literary Award (KLA) tahun lalu. Melalui buku yang dicetak dengan biaya sendiri itu, Urip melenggang mantap, terjun ke arena puisi.
“Tetapi sebetulnya saya sudah menulis puisi sejak SMA”, katanya memulai kisah. Itu berarti antara tahun 1981-1984. Tak sekadar menulis, ia pun pernah pula mengikuti lomba baca puisi serta aktif di beberapa komunitas sastra, seperti Gorong-Gorong Budaya dan Apresiasi Sastra. Putra kedua pasangan Kresno Kambali dan Soebijarsinih Soehoed–keduanya telah almarhum–ini mengaku tertarik pula pada filsafat dan wayang. Rumitnya filsafat sempat membawa Urip singgah sejenak menekuni ibu segala ilmu tersebut di STF Driyarkara meski tak selesai (1992-1993). Dua tahun sebelumnya, penggemar berat sajak-sajak Goenawan Mohamad dan Joko Pinurbo ini, menamatkan kuliahnya di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1990).
Adapun wayang adalah yang memunculkan gagasan di kepala lelaki berusia 42 tahun ini untuk menerbitkan antologi puisinya yang kedua. Buku yang diluncurkan pada 9 November 2007 lalu diberi judul Karna, Ksatria di Jalan Panah. Acara launching-nya berlangsung di Café Omah Sendok, Jakarta Selatan. Dihadiri segenap sahabat dan kerabat Urip dari berbagai kalangan, termasuk pendukung utamanya: teman-teman di Perkumpulan Meditasi Bali Usada.
Telah lama pegawai media internal di sebuah BUMN ini menggeluti meditasi ala buddhis. Di perkumpulan ini pula Urip memperoleh bantuan dana bagi penerbitan buku puisinya tersebut yang memakan biaya lebih dari sepuluh juta rupiah.
“Meskipun saya pernah masuk lima besar KLA 2006, tetapi ternyata bukan jaminan bisa dengan mudah menembus para penerbit”, ujar Urip dengan wajah prihatin.
Demikianlah adanya kenyataan di negeri ini. Puisi belum mendapat tempat yang “layak” di ranah sastra kita. Layak di sini bermakna tidak banyak penggemar (pembaca), tidak seperti prosa. Sehingga para penerbit mesti berhitung dengan sangat cermat sebelum memutuskan untuk menerbitkan sebuah buku puisi. Lantaran itulah Urip lantas memilih menerbitkan sendiri karyanya secara swadaya dan swadana.
Menyangkut perkara ide sebuah puisi, Urip bisa memulungnya dari mana saja. Namun, khusus untuk buku-buku yang telah dan kelak akan diterbitkannya, ia menciptakan sajak-sajak tematis yang dipikirkan dan direncanakan masak-masak. Antologi tematis seperti Karna ini merupakan salah satu obsesinya dalam berpuisi.
Dan tentang Karna, Urip mendapatkan ilhamnya pertama kali usai membaca Mahabharata hasil gubahan Purwadi sekitar dua tahun silam. Saat itu, pria kurus kelahiran 15 Juli 1965 ini baru ngeh dan merasa jatuh cinta pada karakter si “Anak Haram”, Karna yang gugur secara ksatria di tangan Arjuna di medan perang Bharata Yudha.
Sesungguhnya, pewayangan bukanlah barang baru dan asing bagi Urip. Sejak kecil ia telah dikenalkan oleh sang ayah kepada kesenian ini. Pun ia juga melahap dengan rakusnya kisah-kisah wayang tersebut lewat majalah Si Kuncung yang terbit pada 1970-an serta versi komik Mahabharata karya R.A.Kosasih yang legendaris itu. Belakangan, bacaannya tentang wayang (Mahabharata dan Ramayana) meluas hingga ke banyak versi. Misalnya, versi India karya P.Lal terbitan Balai Pustaka. Dari kitab-kitab yang dibacanya itu, urip menemukan beberapa perbedaan yang mencolok dan bertolak belakang, khususnya pada tokoh Karna.
Dalam versi India, dituturkan bahwa tidak banyak yang tahu Karna itu sebenarnya adalah saudara seibu dengan Pandawa Lima. Ibu mereka, Kunti, sebelum kawin dengan Pandu Dewanata, telah lebih dulu melahirkan Karna dari hasil hubungan cinta dengan Batara Surya. Sementara menurut lakon wayang Jawa, para Pandawa dan Karna telah mengetahui bahwa mereka adalah kakak beradik.
Setelah melalui perenungan yang dalam, Urip memutuskan untuk setia pada alur kisah dari negeri Mahatma Gandhi. Pertimbangannya semata-mata demi dramatika cerita dan mendapatkan efek puitik untuk sajak-sajaknya. Maka, lahirlah 23 puisi bertopik Karna, sejak kelahiran hingga ajalnya. Semua terangkum dalam buku yang sudah disebut di atas tadi.
Nah, sebagaimana yang dicita-citakannya, kini Urip telah mulai merancang buku antologi puisi selanjutnya. Kepinginnya sih bisa terbit secara berkala setiap dua tahun. Di benaknya telah ada konsep tema “mimpi dalam mimpi” yang menunggu direalisasikan. Akankah Urip sanggup terus tegar berkecimpung bersama puisi-puisi yang telah menjadi “jalan hidup”-nya, kendati, seperti kata Wayan Sunarta, nasib puisi (di negeri ini masih) seperti kisah Karna? Semoga saja….***
Endah Sulwesi
Saturday, November 24, 2007,10:53 AM
 Monolog "Sarimin"
Monolog "Sarimin"
POTRET BURAM WAJAH HUKUM KITA
Selama lima malam berturut-turut (14-18 November 2007), Butet Kartaredjasa, berhasil memukau khalayak penonton lewat pertunjukan drama monolog berjudul Sarimin. Atas permintaan banyak penggemarnya, akhirnya panitia Art Summit memenuhi permintaan untuk memperpanjang semalam lagi. Pertunjukan yang digelar di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta ini merupakan salah satu mata acara dari rangkaian besar hajatan Art Summit Indonesia V-2007.
Mengusung naskah garapan Agus Noor, Butet tampil prima di hari pertama show-nya. Masih dengan bumbu dagelan yang khas, putra kelima dari seniman besar Bagong Kussudiardja (alm) ini bukan saja sukses menghibur para hadirin tetapi juga kembali menunjukkan kelasnya sebagai aktor teater dan “Raja Monolog”. Untuk kesekian kalinya berkolaborasi dengan adik kandungnya, Djaduk Ferianto selaku peñata musik, Butet beraksi dengan memboyong spirit teater tradisional ke atas panggung. Terasa sekali bekas-bekas pengaruh Teater Gandrik, kelompok teater asal Yogyakarta yang turut membesarkan ‘karier’ kesenimanan kedua kakak beradik ini. Mengandalkan improvisasi–walaupun tetap mesti patuh pada skenario–pertunjukan monolog tersebut mengalir akrab dan menyatu dengan publik pemirsanya. Mirip lenong Betawi.
Butet yang lahir pada 21 November 1961 dan telanjur lekat dengan predikat tukang banyol itu, kembali melemparkan kritik-kritik sosial lewat lakon tukang topeng monyet ini. Kali ini temanya tentang kebobrokan hukum di negeri bernama Indonesia.
Gagasan awalnya datang dari seorang ahli dan praktisi hukum, Pradjoto, yang terobsesi mengangkat tema hukum ke atas panggung dalam kemasan monolog. Bak gayung bersambut, tawaran itu akhirnya diterima Agus Noor dan Butet, walaupun semula mereka sempat gemetar juga. Segera mereka menyiapkan naskah dan segala sesuatunya. Maka, lantas terciptalah lakon komedi Sarimin, seorang lelaki berusia 54 tahun yang berprofesi sebagai tukang topeng monyet keliling. Semula Agus Noor memberi nama tokohnya Saridin, namun agar lebih ”identik” dengan profesi topeng monyet, diganti Sarimin.
Suatu hari, secara tak sengaja Sarimin menemukan selembar Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lantaran buta huruf, Sarimin tidak tahu siapa pemilik KTP tersebut. Dengan lugu dan berbekal niat baik, Sarimin menyerahkan KTP tersebut ke kantor polisi. Maksudnya agar kelak polisi saja yang mengantarkan ke pemiliknya.
Namun, sial sekali Sarimin. Di kantor polisi itu alih-alih mendapat pujian karena telah berbuat baik, ia malah mendapat masalah. Petugas polisi yang menerimanya justru mempersulit urusan dengan berusaha memeras Sarimin dan mengancam akan mengurungnya di penjara, sebab ternyata KTP itu kepunyaan Hakim Agung. Sarimin dituduh sebagai pencuri karena tidak segera mengembalikannya.
Sarimin yang malang tak bisa membela diri. Akibatnya secara semena-mena ia dijebloskan ke sel tahanan. Pengacara yang ditunjuk untuk membelanya malah sibuk mencari popularitas sendiri. Sarimin hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Sungguh, hukum dan keadilan bukan milik orang kecil seperti dirinya.
Kisah Sarimin ini mencerminkan wajah peradilan dan hukum di negeri kita yang suram dan carut-marut; penuh praktik suap-menyuap, nepotisme, korupsi, dan kolusi. Mulai dari petugas polisi di tingkat bawah hingga para hakim, jaksa, dan pengacara di jajaran atas. Jual beli perkara sudah menjadi rahasia umum yang lumrah. Keadilan untuk semua hanya berhenti pada jargon dan slogan kosong belaka.
Tokoh Sarimin merupakan perwakilan ‘orang kecil’ yang jujur kendati tak pernah mengecap bangku sekolah dan buta hukum sama sekali. Kejujuran sudah tak laku lagi dijual di sini. Segalanya mesti pakai uang, uang, dan uang. Jika punya masalah dengan hukum, lebih baik selesaikan secara kekeluargaan, sebab jika dibawa ke polisi atau meja hijau, urusannya akan bertambah panjang dan rumit. Mengadu kehilangan ayam, bisa-bisa kita malah jadi kehilangan kambing.
Monolog yang berdurasi sekitar 100 menit ini, dari awal hingga akhir mampu membuat penonton ger-geran. Butet seolah-olah tengah mendongengi penonton. Beberapa kali ia bahkan melibatkan penonton dalam dialognya. Butet juga melakukan sendiri perubahan setting panggung, menggeser-geser dan memindah-mindahkan properti. Sesekali Djaduk dan awak musik lainnya ikut nyeletuk. Sekali lagi, mengingatkan kita pada gaya Teater Gandrik.
Suksesnya pertunjukan monodrama ini tak lepas dari sebuah kerja sama tim yang solid. Mereka antara lain : Ong Harry Wahyu (Penata Artistik), Zuki atau yang lebih dikenal dengan nama Kill The DJ (Pengontrol Dramatik), Felix Antonius Widyatmoko (Penata Suara), Rulyani Isfihana (Penata Busana), dll.
Berikutnya, monolog ini akan digelar juga di Yogyakarta pada 26 dan 27 November 2007. Mestinya, dalam setiap pergelaran, diundang pula para pejabat polisi dan pengadilan setempat. Siapa tahu kritik-kritik yang dilontarkan bisa lebih efektif karena langsung sampai ke sasarannya. ***
(Endah Sulwesi)
Selama lima malam berturut-turut (14-18 November 2007), Butet Kartaredjasa, berhasil memukau khalayak penonton lewat pertunjukan drama monolog berjudul Sarimin. Atas permintaan banyak penggemarnya, akhirnya panitia Art Summit memenuhi permintaan untuk memperpanjang semalam lagi. Pertunjukan yang digelar di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta ini merupakan salah satu mata acara dari rangkaian besar hajatan Art Summit Indonesia V-2007.
Mengusung naskah garapan Agus Noor, Butet tampil prima di hari pertama show-nya. Masih dengan bumbu dagelan yang khas, putra kelima dari seniman besar Bagong Kussudiardja (alm) ini bukan saja sukses menghibur para hadirin tetapi juga kembali menunjukkan kelasnya sebagai aktor teater dan “Raja Monolog”. Untuk kesekian kalinya berkolaborasi dengan adik kandungnya, Djaduk Ferianto selaku peñata musik, Butet beraksi dengan memboyong spirit teater tradisional ke atas panggung. Terasa sekali bekas-bekas pengaruh Teater Gandrik, kelompok teater asal Yogyakarta yang turut membesarkan ‘karier’ kesenimanan kedua kakak beradik ini. Mengandalkan improvisasi–walaupun tetap mesti patuh pada skenario–pertunjukan monolog tersebut mengalir akrab dan menyatu dengan publik pemirsanya. Mirip lenong Betawi.
Butet yang lahir pada 21 November 1961 dan telanjur lekat dengan predikat tukang banyol itu, kembali melemparkan kritik-kritik sosial lewat lakon tukang topeng monyet ini. Kali ini temanya tentang kebobrokan hukum di negeri bernama Indonesia.
Gagasan awalnya datang dari seorang ahli dan praktisi hukum, Pradjoto, yang terobsesi mengangkat tema hukum ke atas panggung dalam kemasan monolog. Bak gayung bersambut, tawaran itu akhirnya diterima Agus Noor dan Butet, walaupun semula mereka sempat gemetar juga. Segera mereka menyiapkan naskah dan segala sesuatunya. Maka, lantas terciptalah lakon komedi Sarimin, seorang lelaki berusia 54 tahun yang berprofesi sebagai tukang topeng monyet keliling. Semula Agus Noor memberi nama tokohnya Saridin, namun agar lebih ”identik” dengan profesi topeng monyet, diganti Sarimin.
Suatu hari, secara tak sengaja Sarimin menemukan selembar Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lantaran buta huruf, Sarimin tidak tahu siapa pemilik KTP tersebut. Dengan lugu dan berbekal niat baik, Sarimin menyerahkan KTP tersebut ke kantor polisi. Maksudnya agar kelak polisi saja yang mengantarkan ke pemiliknya.
Namun, sial sekali Sarimin. Di kantor polisi itu alih-alih mendapat pujian karena telah berbuat baik, ia malah mendapat masalah. Petugas polisi yang menerimanya justru mempersulit urusan dengan berusaha memeras Sarimin dan mengancam akan mengurungnya di penjara, sebab ternyata KTP itu kepunyaan Hakim Agung. Sarimin dituduh sebagai pencuri karena tidak segera mengembalikannya.
Sarimin yang malang tak bisa membela diri. Akibatnya secara semena-mena ia dijebloskan ke sel tahanan. Pengacara yang ditunjuk untuk membelanya malah sibuk mencari popularitas sendiri. Sarimin hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Sungguh, hukum dan keadilan bukan milik orang kecil seperti dirinya.
Kisah Sarimin ini mencerminkan wajah peradilan dan hukum di negeri kita yang suram dan carut-marut; penuh praktik suap-menyuap, nepotisme, korupsi, dan kolusi. Mulai dari petugas polisi di tingkat bawah hingga para hakim, jaksa, dan pengacara di jajaran atas. Jual beli perkara sudah menjadi rahasia umum yang lumrah. Keadilan untuk semua hanya berhenti pada jargon dan slogan kosong belaka.
Tokoh Sarimin merupakan perwakilan ‘orang kecil’ yang jujur kendati tak pernah mengecap bangku sekolah dan buta hukum sama sekali. Kejujuran sudah tak laku lagi dijual di sini. Segalanya mesti pakai uang, uang, dan uang. Jika punya masalah dengan hukum, lebih baik selesaikan secara kekeluargaan, sebab jika dibawa ke polisi atau meja hijau, urusannya akan bertambah panjang dan rumit. Mengadu kehilangan ayam, bisa-bisa kita malah jadi kehilangan kambing.
Monolog yang berdurasi sekitar 100 menit ini, dari awal hingga akhir mampu membuat penonton ger-geran. Butet seolah-olah tengah mendongengi penonton. Beberapa kali ia bahkan melibatkan penonton dalam dialognya. Butet juga melakukan sendiri perubahan setting panggung, menggeser-geser dan memindah-mindahkan properti. Sesekali Djaduk dan awak musik lainnya ikut nyeletuk. Sekali lagi, mengingatkan kita pada gaya Teater Gandrik.
Suksesnya pertunjukan monodrama ini tak lepas dari sebuah kerja sama tim yang solid. Mereka antara lain : Ong Harry Wahyu (Penata Artistik), Zuki atau yang lebih dikenal dengan nama Kill The DJ (Pengontrol Dramatik), Felix Antonius Widyatmoko (Penata Suara), Rulyani Isfihana (Penata Busana), dll.
Berikutnya, monolog ini akan digelar juga di Yogyakarta pada 26 dan 27 November 2007. Mestinya, dalam setiap pergelaran, diundang pula para pejabat polisi dan pengadilan setempat. Siapa tahu kritik-kritik yang dilontarkan bisa lebih efektif karena langsung sampai ke sasarannya. ***
(Endah Sulwesi)
Wednesday, November 21, 2007,2:42 PM
 Delapan Penyair Unjuk Puisi di TUK
Delapan Penyair Unjuk Puisi di TUK
Mendung menggantung di langit Jakarta sejak siang pada akhir pekan lalu yang disusul kemudian oleh hujan lebat pada petang harinya. Jakarta sekejap menjadi basah dan sebagian orang memilih untuk tinggal nyaman di rumah. Tetapi hujan rupanya tak menyurutkan langkah segelintir orang untuk tetap mendatangi Teater Utan Kayu (TUK) yang senja itu menggelar pembacaan puisi delapan penyair muda Tanah Air. Ini merupakan agenda berkala TUK yang mencoba memantau perkembangan sastrawan muda Indonesia.
Kedelapan mereka adalah: Hasan Aspahani (Batam), Fadjroel Rachman dan Binhad Nurrohmat (Jakarta), Pranita Dewi (Bali), Inggit Putria Marga dan Lupita Lukman (Lampung), S. Yoga (Jawa Timur), serta Dina Oktaviani (Yogyakarta). Selama dua hari (9-10 November 2007) mereka tampil membawakan sajak masing-masing.
Pada malam kedua, giliran Pranita Dewi, Binhad Nurrohmat, Inggit Putria Marga, dan S.Yoga yang menunjukkan kebolehannya membaca puisi setelah malam sebelumnya tampil Hasan, Fadjroel, Dina, dan Lupita Lukman.
Mereka semua memang penyair (penulis puisi) yang rata-rata sudah menerbitkan buku, tetapi bukan ”pembaca” puisi. Oleh karena itu, harap maklum saja jika aksi panggung mereka cenderung datar dan biasa-biasa saja. Gerak tubuh, mimik wajah, serta olah vokal mereka juga tidak ada yang tampak luar biasa. Mereka telah berusaha semaksimal mungkin, namun, apa mau dikata, hasilnya tetap tak istimewa.
Binhad, misalnya, berupaya mencairkan suasana dengan melontarkan lelucon-lelucon sebagai improvisasi. Awalnya cukup berhasil mengajak penonton tergelak. Tetapi, tak bertahan lama. Audiens yang tak banyak itu segera merasa jenuh.
Lalu Fadjroel, mencoba bergaya teatrikal dengan naik ke atas kursi ketika membacakan satu sajaknya yang berjudul “Secangkir Kopi Pagi” yang dicuplik dari buku Dongeng untuk Poppy. Barangkali merasa lebih bebas dan cair ketika dia membacakan sajak itu pada acara launching di MP Book Point beberapa bulan lalu. Bersama-sama Binhad dengan Bau Betina-nya, Fadjroel masuk ke dalam sepuluh besar kandidat penerima Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2007 untuk kategori puisi.
Selanjutnya ada Dina Oktaviani melantunkan “Hantu-Hantu Tanjung Karang” dengan vokal sedikit gemetar. Padahal, ketika suaranya menjadi ”surat yang disuarakan” dalam rekaman untuk pertunjukan cerpenis mantan suaminya, Gunawan Maryanto dalam Festival Sastra International dua tahun lalu di tempat yang sama, sangat memukau. Tak beda jauh dengan Dina, demikian pula Pranita Dewi, Si “Pelacur Para Dewa” dan Lupita Lukman saat membaca karya mereka.
Yang agak lumayan barangkali Inggit Putria Marga. Tanpa banyak lagak, cukup duduk tenang di kursi kayu yang tersedia, penyair Lampung ini membawa penonton sejenak larut bersama puisinya. Mungkin dengan cara seperti ini, makna puisi lebih merasuk sukma, dan pesan penyair sampai dengan baik.
Ya, menulis puisi memang tak sama dengan membaca puisi. Dan kita, para penikmat ini, tak bisa menuntut para penyair itu untuk juga piawai sebagai pembaca puisi. Tak banyak yang bisa melakukan keduanya dengan baik. Rasanya bisa dihitung jari, sebut saja Rendra, Sutardji Calzoum Bachri, dan almarhum Hamid Jabbar yang mampu menyihir kita. ***
Kedelapan mereka adalah: Hasan Aspahani (Batam), Fadjroel Rachman dan Binhad Nurrohmat (Jakarta), Pranita Dewi (Bali), Inggit Putria Marga dan Lupita Lukman (Lampung), S. Yoga (Jawa Timur), serta Dina Oktaviani (Yogyakarta). Selama dua hari (9-10 November 2007) mereka tampil membawakan sajak masing-masing.
Pada malam kedua, giliran Pranita Dewi, Binhad Nurrohmat, Inggit Putria Marga, dan S.Yoga yang menunjukkan kebolehannya membaca puisi setelah malam sebelumnya tampil Hasan, Fadjroel, Dina, dan Lupita Lukman.
Mereka semua memang penyair (penulis puisi) yang rata-rata sudah menerbitkan buku, tetapi bukan ”pembaca” puisi. Oleh karena itu, harap maklum saja jika aksi panggung mereka cenderung datar dan biasa-biasa saja. Gerak tubuh, mimik wajah, serta olah vokal mereka juga tidak ada yang tampak luar biasa. Mereka telah berusaha semaksimal mungkin, namun, apa mau dikata, hasilnya tetap tak istimewa.
Binhad, misalnya, berupaya mencairkan suasana dengan melontarkan lelucon-lelucon sebagai improvisasi. Awalnya cukup berhasil mengajak penonton tergelak. Tetapi, tak bertahan lama. Audiens yang tak banyak itu segera merasa jenuh.
Lalu Fadjroel, mencoba bergaya teatrikal dengan naik ke atas kursi ketika membacakan satu sajaknya yang berjudul “Secangkir Kopi Pagi” yang dicuplik dari buku Dongeng untuk Poppy. Barangkali merasa lebih bebas dan cair ketika dia membacakan sajak itu pada acara launching di MP Book Point beberapa bulan lalu. Bersama-sama Binhad dengan Bau Betina-nya, Fadjroel masuk ke dalam sepuluh besar kandidat penerima Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2007 untuk kategori puisi.
Selanjutnya ada Dina Oktaviani melantunkan “Hantu-Hantu Tanjung Karang” dengan vokal sedikit gemetar. Padahal, ketika suaranya menjadi ”surat yang disuarakan” dalam rekaman untuk pertunjukan cerpenis mantan suaminya, Gunawan Maryanto dalam Festival Sastra International dua tahun lalu di tempat yang sama, sangat memukau. Tak beda jauh dengan Dina, demikian pula Pranita Dewi, Si “Pelacur Para Dewa” dan Lupita Lukman saat membaca karya mereka.
Yang agak lumayan barangkali Inggit Putria Marga. Tanpa banyak lagak, cukup duduk tenang di kursi kayu yang tersedia, penyair Lampung ini membawa penonton sejenak larut bersama puisinya. Mungkin dengan cara seperti ini, makna puisi lebih merasuk sukma, dan pesan penyair sampai dengan baik.
Ya, menulis puisi memang tak sama dengan membaca puisi. Dan kita, para penikmat ini, tak bisa menuntut para penyair itu untuk juga piawai sebagai pembaca puisi. Tak banyak yang bisa melakukan keduanya dengan baik. Rasanya bisa dihitung jari, sebut saja Rendra, Sutardji Calzoum Bachri, dan almarhum Hamid Jabbar yang mampu menyihir kita. ***
endah sulwesi 13/11
Thursday, November 08, 2007,10:41 AM
 OKA RUSMINI : “Menulis itu, buat saya adalah semacam terapi jiwa.”
OKA RUSMINI : “Menulis itu, buat saya adalah semacam terapi jiwa.”
Malam masih muda saat saya bertandang ke sebuah rumah mungil bercat kuning cerah di kompleks Perumahan Purnawira, Denpasar, Bali pada akhir Oktober silam. Seorang perempuan bertubuh kurus–nyaris ceking–mengenakan tank top yang juga berwarna kuning, menyambut dengan hangat. Dialah sang nyonya rumah, Oka Rusmini.
“Aku baru pulang kantor, nih,” ujarnya sembari mempersilakan saya masuk. Tubuhnya masih basah oleh keringat. Seorang bocah kecil mengintil di belakangnya. “Ini Pasha, anakku. Baru disunat dia,” Oka memperkenalkan putra semata wayangnya itu. Selanjutnya kami mengobrol akrab di ruang tamu yang dinding-dindingnya meriah oleh aneka foto Oka dan keluarga.
Oka Rusmini memang seorang pribadi yang ceria dan cepat akrab dengan siapapun. Segera saja kami merasa bagai bicara dengan seorang sahabat yang telah lama tak berjumpa. Padahal, baru kali itulah kami saling bertemu.
Nama Oka Rusmini mulai bersinar sejak novelnya Tarian Bumi (2000) diluncurkan. Novel yang mengusung isu feminisme dengan mengetengahkan persoalan perempuan Bali dalam belitan kultur dan agama (Hindu) tersebut membuat nama Oka Rusmini berkibar di blantika sastra Tanah Air, kendati kiprah kepenulisan perempuan kelahiran 11 Juli 1967 ini telah dimulai jauh sebelumnya. Karya pertamanya yang dipublikasi adalah Monolog Pohon (1997) berupa kumpulan cerita pendek (cerpen). Seterusnya, karya-karyanya yang lain, baik berbentuk puisi atau pun prosa, terus mengalir. Beberapa di antaranya bahkan mendapat penghargaan sebagai yang terbaik.
Sifat periang istri dari penyair dan esais Arief Bagus Prasetyo ini sangat bertolak belakang dengan masa kecilnya yang tidak terlalu manis untuk dikenang. Kedua orang tuanya bercerai ketika Oka berusia 6 tahun. Ia lalu diasuh oleh ayahnya yang kemudian menikah lagi. Sebagai anak perempuan produk keluarga broken home, Oka tumbuh “sendirian”. Tak ada ibu atau kakak–ia anak sulung dari 2 bersaudara–yang bisa diajak curhat. Hanya kepada buku hariannya Oka menumpahkan segala gundah hatinya. Lantaran itulah, “Menulis, buat saya, adalah semacam terapi jiwa,” katanya. Tetapi anehnya, buku harian yang ditulisnya, selalu akan dibakarnya pada hari ulang tahunnya. Itu dilakukannya selama bertahun-tahun.
Barangkali dari situlah awal Oka menyadari bakatnya sebagai penulis. “Kenanga saya tulis waktu SMA, loh,” kenang Oka sambil menunjuk foto cover novel Kenanga di dinding. Novel itu pun memuat kisah perempuan Bali yang terpuruk karena adat dan tradisi di kampungnya. Walaupun menurut pengakuannya ia tak pernah berniat mengkhususkan diri menulis tentang perempuan (dan Bali), namun publik telanjur memberinya stempel sebagai seorang penulis fiksi feminis.
“Sebetulnya, saya ingin menjadikan tulisan-tulisan saya ini sebagai sebuah dokumentasi, khususnya (dokumentasi) Bali,” papar Oka lebih lanjut. “Sebab, saya percaya segala (tradisi) yang pernah terjadi di Bali, kelak akan punah, tergerus zaman”. Masih menurut Oka, persoalan perempuan di Bali (dan di manapun) adalah persoalan kultur dan agama; dan perempuan itu sendirilah yang paling mengerti dirinya. Oleh karena itu, perempuan pulalah yang mesti menuliskannya.
Trauma perceraian orang tuanya sempat membuat Oka berniat tidak menikah. Namun, kekerasan hatinya luluh oleh cinta seorang pria Jawa yang kini menjadi suaminya itu. Dari perkawinan mereka lahirlah Pasha Renaisan (6). Perkawinan ini harus “dibayar” mahal oleh Oka yang berkasta Brahmana. Ia harus menerima nasib seperti tokoh-tokoh perempuan (Bali) rekaannya : “dibuang” dari keluarga karena menikah dengan seorang pria muslim (beda kasta). Ia sendiripun lantas memutuskan memeluk agama Islam.
“Saya tidak pernah mengira akan menikah dan punya anak. Setelah Pasha lahir, saya baru sadar, ternyata saya hanyalah seorang ibu yang sangat konservatif; yang selalu khawatir akan keselamatan anaknya”, kata penggemar novel Cantik Itu Luka (Eka Kurniawan) seraya tersenyum sumringah.
Di samping terus menulis, Oka Rusmini juga bekerja sebagai redaktur fashion di Bali Post, koran lokal terbesar di Bali. Sesekali ia juga menghadiri undangan selaku pembicara pada forum-forum sastra nasional maupun internasional seperti Ubud Writers and Readers Festival di Bali serta Festival Sastra Winternachten di Belanda beberapa waktu lalu. Ia juga pernah diundang sebagai penulis tamu di Universitas Hamburg, Jerman (2003).
Kepiawaian Oka menulis tak perlu disangsikan lagi. Berbagai penghargaan telah diraihnya. Dimulai pada 1994 ketika cerpennya yang berjudul “Putu Menolong Tuhan” terpilih sebagai cerpen terbaik majalah Femina. Disusul oleh “Sagra” yang memenangi sayembara novelet di majalah yang sama pada 1998. Lalu giliran majalah sastra Horison mengganjar cerpen karyanya, “Pemahat Abad” sebagai cerpen terbaik 1990-2000. Kemudian pada 2003 ia dinobatkan sebagai “Penerima Penghargaan Penulisan Karya Sastra 2003” berkat novel Tarian Bumi.
Kini, wanita pemilik nama lengkap Ida Ayu Oka Rusmini, tengah menanti kelahiran novel terbarunya yang diberi tajuk Tempurung. Apakah masih berkutat pada Bali dan persoalan perempuan? Baiklah, kita lihat saja nanti.***
Biodata singkat:
Nama Lengkap: Ida Ayu Oka Rusmini
Tempat/tgl.lahir: Jakarta, 11 Juli 1967
Pendidikan: Fakultas Sastra Universitas Udayana
Pekerjaan: Redaktur Fashion Bali Post
Suami: Arief Bagus Prasetyo
Anak: Pasha Renaisan (6 tahun)
Buku : Monolog Pohon (1997), Tarian Bumi (2000), Sagra (2001), Kenanga (2003), Patiwangi (2003), dan Warna Kita (2007).
Endah Sulwesi 6/11
“Aku baru pulang kantor, nih,” ujarnya sembari mempersilakan saya masuk. Tubuhnya masih basah oleh keringat. Seorang bocah kecil mengintil di belakangnya. “Ini Pasha, anakku. Baru disunat dia,” Oka memperkenalkan putra semata wayangnya itu. Selanjutnya kami mengobrol akrab di ruang tamu yang dinding-dindingnya meriah oleh aneka foto Oka dan keluarga.
Oka Rusmini memang seorang pribadi yang ceria dan cepat akrab dengan siapapun. Segera saja kami merasa bagai bicara dengan seorang sahabat yang telah lama tak berjumpa. Padahal, baru kali itulah kami saling bertemu.
Nama Oka Rusmini mulai bersinar sejak novelnya Tarian Bumi (2000) diluncurkan. Novel yang mengusung isu feminisme dengan mengetengahkan persoalan perempuan Bali dalam belitan kultur dan agama (Hindu) tersebut membuat nama Oka Rusmini berkibar di blantika sastra Tanah Air, kendati kiprah kepenulisan perempuan kelahiran 11 Juli 1967 ini telah dimulai jauh sebelumnya. Karya pertamanya yang dipublikasi adalah Monolog Pohon (1997) berupa kumpulan cerita pendek (cerpen). Seterusnya, karya-karyanya yang lain, baik berbentuk puisi atau pun prosa, terus mengalir. Beberapa di antaranya bahkan mendapat penghargaan sebagai yang terbaik.
Sifat periang istri dari penyair dan esais Arief Bagus Prasetyo ini sangat bertolak belakang dengan masa kecilnya yang tidak terlalu manis untuk dikenang. Kedua orang tuanya bercerai ketika Oka berusia 6 tahun. Ia lalu diasuh oleh ayahnya yang kemudian menikah lagi. Sebagai anak perempuan produk keluarga broken home, Oka tumbuh “sendirian”. Tak ada ibu atau kakak–ia anak sulung dari 2 bersaudara–yang bisa diajak curhat. Hanya kepada buku hariannya Oka menumpahkan segala gundah hatinya. Lantaran itulah, “Menulis, buat saya, adalah semacam terapi jiwa,” katanya. Tetapi anehnya, buku harian yang ditulisnya, selalu akan dibakarnya pada hari ulang tahunnya. Itu dilakukannya selama bertahun-tahun.
Barangkali dari situlah awal Oka menyadari bakatnya sebagai penulis. “Kenanga saya tulis waktu SMA, loh,” kenang Oka sambil menunjuk foto cover novel Kenanga di dinding. Novel itu pun memuat kisah perempuan Bali yang terpuruk karena adat dan tradisi di kampungnya. Walaupun menurut pengakuannya ia tak pernah berniat mengkhususkan diri menulis tentang perempuan (dan Bali), namun publik telanjur memberinya stempel sebagai seorang penulis fiksi feminis.
“Sebetulnya, saya ingin menjadikan tulisan-tulisan saya ini sebagai sebuah dokumentasi, khususnya (dokumentasi) Bali,” papar Oka lebih lanjut. “Sebab, saya percaya segala (tradisi) yang pernah terjadi di Bali, kelak akan punah, tergerus zaman”. Masih menurut Oka, persoalan perempuan di Bali (dan di manapun) adalah persoalan kultur dan agama; dan perempuan itu sendirilah yang paling mengerti dirinya. Oleh karena itu, perempuan pulalah yang mesti menuliskannya.
Trauma perceraian orang tuanya sempat membuat Oka berniat tidak menikah. Namun, kekerasan hatinya luluh oleh cinta seorang pria Jawa yang kini menjadi suaminya itu. Dari perkawinan mereka lahirlah Pasha Renaisan (6). Perkawinan ini harus “dibayar” mahal oleh Oka yang berkasta Brahmana. Ia harus menerima nasib seperti tokoh-tokoh perempuan (Bali) rekaannya : “dibuang” dari keluarga karena menikah dengan seorang pria muslim (beda kasta). Ia sendiripun lantas memutuskan memeluk agama Islam.
“Saya tidak pernah mengira akan menikah dan punya anak. Setelah Pasha lahir, saya baru sadar, ternyata saya hanyalah seorang ibu yang sangat konservatif; yang selalu khawatir akan keselamatan anaknya”, kata penggemar novel Cantik Itu Luka (Eka Kurniawan) seraya tersenyum sumringah.
Di samping terus menulis, Oka Rusmini juga bekerja sebagai redaktur fashion di Bali Post, koran lokal terbesar di Bali. Sesekali ia juga menghadiri undangan selaku pembicara pada forum-forum sastra nasional maupun internasional seperti Ubud Writers and Readers Festival di Bali serta Festival Sastra Winternachten di Belanda beberapa waktu lalu. Ia juga pernah diundang sebagai penulis tamu di Universitas Hamburg, Jerman (2003).
Kepiawaian Oka menulis tak perlu disangsikan lagi. Berbagai penghargaan telah diraihnya. Dimulai pada 1994 ketika cerpennya yang berjudul “Putu Menolong Tuhan” terpilih sebagai cerpen terbaik majalah Femina. Disusul oleh “Sagra” yang memenangi sayembara novelet di majalah yang sama pada 1998. Lalu giliran majalah sastra Horison mengganjar cerpen karyanya, “Pemahat Abad” sebagai cerpen terbaik 1990-2000. Kemudian pada 2003 ia dinobatkan sebagai “Penerima Penghargaan Penulisan Karya Sastra 2003” berkat novel Tarian Bumi.
Kini, wanita pemilik nama lengkap Ida Ayu Oka Rusmini, tengah menanti kelahiran novel terbarunya yang diberi tajuk Tempurung. Apakah masih berkutat pada Bali dan persoalan perempuan? Baiklah, kita lihat saja nanti.***
Biodata singkat:
Nama Lengkap: Ida Ayu Oka Rusmini
Tempat/tgl.lahir: Jakarta, 11 Juli 1967
Pendidikan: Fakultas Sastra Universitas Udayana
Pekerjaan: Redaktur Fashion Bali Post
Suami: Arief Bagus Prasetyo
Anak: Pasha Renaisan (6 tahun)
Buku : Monolog Pohon (1997), Tarian Bumi (2000), Sagra (2001), Kenanga (2003), Patiwangi (2003), dan Warna Kita (2007).
Endah Sulwesi 6/11
Saturday, November 03, 2007,9:01 PM
 Profil di Balik “Bog Bog”
Profil di Balik “Bog Bog”
MADE “JANGO” PRAMARTHA : “Kritik juga bisa disampaikan melalui kartun.”
Bukan saja terkenal akan keelokan alam dan kekayaan budayanya, Bali juga terkenal dengan “Joger”-nya, sebuah toko tempat menjual t-shirt dan aneka cindera mata yang sering menyebut dirinya sebagai “pabrik kata-kata”. Beragam t-shirt dengan motif unik berupa deretan kata-kata lucu itu telah lama ngetop sebagai tempat belanja oleh-oleh. Selain itu juga dijual macam-macam suvenir berupa cangkir, mug, gantungan kunci, topi, asbak, notes, dan lain-lain.
Sejak dua tahun lalu, Joger punya “saingan” bernama Bog Bog. Hampir sama dengan Joger, jualan utama Bog Bog pun kaus oblong. Bedanya dengan Joger yang “menjual” kata-kata, Bog Bog mengandalkan bahasa gambar berupa kartun.
Sejarahnya, Bog Bog merupakan nama sebuah majalah bulanan khusus kartun yang lahir pada 1 April 2001. Tirasnya, sampai hari ini mencapai 10.000 eksemplar setiap bulan dengan harga eceran Rp 7.500,- (Bali) dan Rp 15.000,- (luar Bali) . Ya, pelanggannya bukan hanya terbatas di Bali, tetapi juga di luar Bali dan bahkan luar negeri. Tidak mengherankan, di samping Bog Bog majalah berbahasa Inggris, juga karena gambar (kartun) adalah bahasa universal yang bisa dimengerti siapapun.
Sukses tersebut tak bisa lepas dari sosok pemiliknya, Made Pramartha atau yang lebih beken dipanggil Jango.Pada usia Bog Bog yang keempat, Jango memperoleh gagasan untuk juga membuka toko kaus dan cindera mata dengan merk dagang yang sama. Jango yang sarjana seni rupa itu memang sudah lama sekali menggeluti kartun. Sejak masih menjadi siswa di SMA 3 Denpasar, karya-karyanya telah sering menghiasi lembaran kartun strip di Bali Pos, surat kabar daerah terbesar di Bali.
Setahun setelah menyelesaikan kuliah sarjananya di Universitas Udayana (1991), Jango mendapat tawaran dari seorang dosen berkebangsaan Australia yang terpikat pada karya-karyanya, untuk melanjutkan studi desain grafis di negeri Kangguru. Jango pun hengkang ke sana; memilih University of Western Australia sebagai tempatnya menimba ilmu dan pulang kembali dua tahun kemudian dengan semangat berkarya yang kian besar. Ia percaya pesan dan kritik–terutama kepada para penguasa–dapat disampaikan melalui kartun. Maka lalu, ia menciptakan tokoh kartun Bali bernama Made Bogler dan menerbitkan Bog Bog. Nama Bog Bog diambil dari Bogler yang berarti bohong.
Made Bogler sangat populer di kalangan masyarakat Bali, khususnya para pembacanya. Janggo kerap menyisipkan kritik-kritik dan sindiran lewat tokoh kartun ciptaannya itu. Ia merespons setiap peristiwa penting yang terjadi di negeri ini, khusuanya di tanah kelahirannya, seperti saat bom Bali (2004) atau runtuhnya rezim pemerintahan Soeharto (1998). Sementara itu, di Bali Pos ia tetap mengisi rubrik kartun dengan tokoh lain lagi : Si Gug (orang yang selalu dipersalahkan).
Lantaran kiprah dan komitmennya yang besar terhadap seni kartun, pada 2005 Jango terpilih sebagai Ketua Indonesian Cartoonist Association atau lebih dikenal dengan nama PAKARTI periode 2005-2010, menggantikan ketua sebelumnya, G.M. Suddharta. Beberapa pameran kartun bertaraf internasional telah pernah diikuti oleh bapak tiga orang anak ini. Kartun telah menjadi pilihan hidup pria kelahiran 21 Desember 1965 ini. Di studionya yang juga merangkap sebagai toko, ia bersama delapan orang kartunis, bergelut dengan kartun setiap hari, baik untuk majalah Bog Bog ataupun membuat desain bagi kaus-kaus dagangannya.
Toko kaus dan suvenirnya itu baru berdiri dua tahun lalu. Meski demikian omzet yang diraihnya lumayan menggiurkan. Jango menyebut angka berkisar antara 30-40 juta rupiah setiap bulannya. Ia optimis, di masa yang akan datang, omzet dari dua buah toko miliknya itu–masing-masing berlokasi di Jl. Veteran 39A dan di pusat perbelanjaan Centro, Kuta–bisa lebih besar lagi. Akankah kelak Bog Bog dapat menyamai Joger?
“Bog Bog masih kecil, masih jauh untuk bisa seperti Joger”, jawab Jango. Namun, peluang itu selalu ada, bukan? Nah, bagi Anda yang barangkali belum pernah ke Bog Bog, silakan kunjungi dan dapatkan oleh-oleh Bali yang unik di sana– mulai dari majalah, kaus, cangkir, tas, sampai handuk–bagi teman dan keluarga Anda tercinta.***
Biodata Singkat:
Nama Lengkap: Made Pramartha
Tempat/tgl.lahir: Denpasar, 21 Desember 1965
Pendidikan: Desain Grafis University of Western Australia.
Pekerjaan/Profesi: Kartunis dan Business Director Bog Bog
Endah Sulwesi 3/11